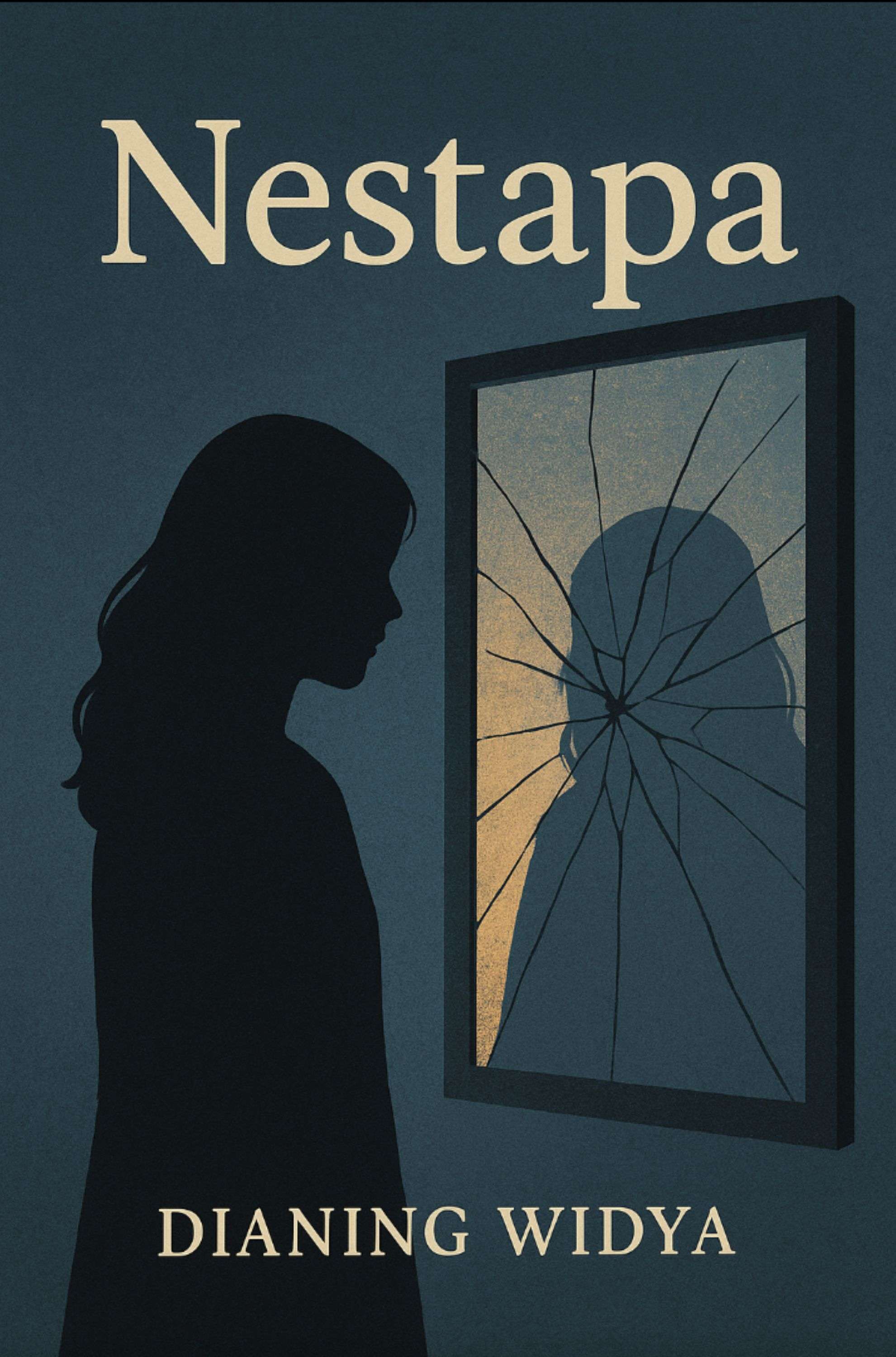KAMI
Orang-orang kerap menyebutku perawan tua. Ya, wajar saja. Usiaku hampir menyentuh kepala empat, tapi aku masih berjalan sendiri.
Aku... Akira, seorang manajer di perusahaan ternama, memang tidak pernah menaruh keinginan untuk menikah. Bagi sebagian orang, pernikahan adalah puncak bahagia. Tapi bagiku, pernikahan justru terdengar menakutkan.
Hari ini aku menemani sahabatku, Henny.
“Ooo, Sayang, sini sama Tante,” ucapku sambil meraih anak keduanya dari gendongan.
“Dia memang masih gampang rewel, Ra,” sahut Henny, sibuk mencari botol susu di dalam tas. Lega rasanya melihat si kecil perlahan tenang dalam gendonganku. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Suara tangisan lain tiba-tiba terdengar dari arah playground tempat makan ini.
Henny buru-buru bangkit, langkahnya tergesa menuju putra pertamanya yang tengah berebut mainan dengan anak pengunjung lain.
Aku hanya bisa memperhatikannya dari jauh, sambil menimang bayi mungil berusia delapan bulan yang kini terlelap di pelukanku. Setelah beberapa saat, Henny kembali. Senyum merekah di wajahnya saat melihat si kecil sudah tertidur pulas dalam gendonganku.
“Alan memang jarang main di playground, Ra. Makan di tempat seperti ini pun bisa dihitung dengan jari,” ujarnya lirih sambil menatap putra sulungnya yang sedang main prosotan.
Aku hanya mengangguk pelan, tanda bahwa aku mendengarnya.
“Oh, sini Abel. Takutnya kamu capek,” katanya seraya mengulurkan tangan meminta anak keduanya.
Aku menggeleng singkat. “Enggak apa-apa, biar Abel sama aku dulu. Kamu makan dulu gih.”
Senyum lembut kembali muncul di wajahnya. “Makasih ya, Ra.”
Aku balas tersenyum, lalu melangkah menuju area bermain. Mengawasi Alan dari jarak dekat, agar Henny bisa makan dengan tenang.
Ingatan lama tiba-tiba menyeruak, saat aku pernah mampir ke rumahnya beberapa bulan lalu. Hari itu, suara tangisan bayi menyambutku sejak di depan pintu. Hatiku langsung tercekat.
“Henny?” panggilku hati-hati, melangkah masuk.
Di ruang tengah, pemandangan itu membuat dadaku sesak. Makanan berserakan di lantai, Alan sibuk dengan mobil-mobilannya sambil sesekali menginjak nasi yang tumpah. Di sisi lain, Abel menangis kencang diatas kasur lantai.
Henny terduduk lemas di lantai, wajahnya pucat, matanya sembab. Begitu melihatku, bibirnya bergetar. “Akira…” suaranya lirih, sebelum akhirnya tangisnya pecah. Aku tak banyak bicara. Langsung menghampirinya dan memeluknya. Biarlah pelukan ini yang bicara.
Aku tahu, di Jakarta ini Henny tak punya siapa-siapa. Dia datang kesini ikut suaminya, tinggal di rumah kontrakan. Dulu, suaminya bekerja di salah satu pabrik. Dua tahun ini, dia tidak bekerja lagi. Itu yang kutahu dari cerita Henny.
Setelah tangis Henny agak reda, aku melepas pelukan perlahan.
“Botol susunya di mana, Hen? Mungkin si adek haus,” tanyaku pelan.
Henny menunduk, lalu menggeleng. Seketika seolah ada pisau menyayat dadaku. Tidak ada susu? Hatiku perih.
“Tunggu sebentar ya. Aku beliin sekarang. Susunya merk apa?” suaraku bergetar menahan panik.
“Apa saja, Ra. Yang penting untuk bayi enam bulan,” jawabnya pelan. Dia menatapku. "Makasih ya, Ra. Nanti kalau udah ada uang, kuganti."
Aku tersenyum lembut mengusap lengannya. "Nggak usah dipikirin," kataku.
Aku bergegas bangkit. Saat melintas di ruang samping, mataku sempat menangkap sosok suaminya. Duduk santai di sofa, menatap televisi dengan wajah datar, seakan hiruk-pikuk di rumah itu bukan apa-apa. Seolah tangisan bayi, tumpahan makanan, dan air mata istrinya hanyalah musik pengantar sore.
“Tante Akira, aku mau minum es boba,” suara Alan menyentakku dari lamunan.
“Baiklah, Sayang, tunggu sebentar di sini, ya,” jawabku sambil berdiri, lalu mengambilkan es boba di meja.
“Maaf, merepotkanmu lagi, Ra,” ucap Henny lembut, tatapannya penuh rasa bersalah.
Aku tersenyum tipis. “Enggak kok, Hen.”
Kuserahkan segelas es boba ke tangan mungil Alan. Anak itu langsung menyesapnya dengan semangat, pipinya mengembung lucu.
Tak lama, sosok yang familiar muncul dari arah pintu. Moana, sahabat kami yang lain. Wajahnya masih sama cantiknya seperti dulu saat kami SMA, seolah tak pernah kalah oleh waktu. Dulu ia primadona sekolah, dan entah bagaimana pesona itu masih melekat erat hingga kini.
“Hai, Henny! Aku kangen banget,” sapa Moana ceria, lalu mereka berpelukan singkat, cipika-cipiki hangat khas pertemuan perempuan.
Aku menghampiri mereka, Moana menoleh padaku. Tatapannya seketika melunak melihat Abel yang terlelap dalam gendonganku.
“Sini, Ra,” katanya pelan, kedua tangannya terulur hati-hati. “Biar aku aja yang gendong. Siapa tahu aku cepet dapat momongan,” suaranya gemetar di ujung kalimat.
Aku terdiam sejenak, lalu dengan perlahan menyerahkan Abel padanya. Moana meraihnya dengan penuh kelembutan, seolah bayi kecil itu adalah permata rapuh yang sudah lama ia nanti.
“Padahal kurasa aku udah cocok jadi ibu, ya kan, Ra?” bisiknya, matanya menerawang. “Tapi… entah kenapa Tuhan belum juga menitipkan.”
Aku tercekat. Tidak tahu harus merespons dengan kata apa. Tentang sabar, Moana sudah pasti paham. Tentang semangat, ia selalu juara dalam hal apapun.
Henny mengusap pelan lengan Moana, memberi dukungan tanpa kata. Aku tahu, sama sepertiku, ia juga tidak menemukan kalimat yang tepat.
“Untung kamu chat aku, Ra. Kalau enggak, mungkin aku sudah menangis sendirian di kamar," lanjut Moana lirih sambil menatap Abel di pelukannya. “Aku dan mertua… tadi pagi ikut acara syukuran empat bulanan tetangga satu RT,” suara Moana serak, matanya sudah berkaca-kaca. “Kalian tahu apa yang beliau katakan?”
Aku segera duduk di sampingnya, menatap penuh perhatian.
“Di depan banyak orang, mertuaku bilang aku perempuan nggak subur. Tanah gersang. Nggak bisa ngasih dia cucu.” Suaranya pecah, isakan lolos dari bibirnya. Air mata jatuh satu per satu, membasahi pipinya.
Aku refleks merangkul bahunya. Henny pun ikut mendekat, memeluk Moana dari sisi lain. Kami bertiga saling erat, seakan pelukan itu ingin mengatakan, kau tidak sendiri.
"Sakit banget rasanya," lirih Moana.
Moana adalah pejuang garis dua dalam usia pernikahannya yang menginjak 10 tahun.
“Orang kayak gitu musuhnya cuma lantai licin, Mo,” celetuk Henny, mencoba mencairkan suasana. “Mau aku beliin minyak bekas nggak, biar makin gampang kepleset?” godanya dengan wajah pura-pura serius.
Di sela-sela isaknya, bibir Moana akhirnya melengkung tipis. Senyum kecil itu, walau samar, jadi cahaya di antara luka.
“Eh, kamu pesen makanan dulu nggak sih,” kataku sambil menyodorkan buku menu ke arahnya. “Kalau lagi kesel, harus makan banyak, Mo. Anggap aja lagi ngunyah omongan mertua.”
Moana mengusap air matanya dengan tisu, kali ini senyumnya lebih lebar meski masih sembab. “Ya udah, aku mau makan yang banyak.”
Setelah selesai makan dan saling bercerita, Moana pamit pulang lebih dulu.
“Suamiku bentar lagi pulang kerja, aku cabut duluan ya,” katanya seraya meraih tasnya.
Aku dan Henny mengangguk.
“Mo, selama suamimu ada di pihakmu, dunia akan tetap baik-baik saja. Semangat, ya,” ujar Henny dengan senyum tulus.
Moana menatapnya, mengangguk pelan. “Iya… semoga dia selalu di pihakku. Kadang aku suka ketar-ketir, Hen. Takut suatu saat nanti dia lelah bareng aku, lalu termakan hasutan ibunya buat cari istri lagi.” Suaranya bergetar, ada cemas yang tak bisa disembunyikan.
“Aku yakin suamimu nggak akan begitu, Mo,” balas Henny lembut. “Semangat pupuk cinta kalian ya.”
“Semangat,” seru Moana, berusaha menguatkan dirinya sendiri. Ia lalu membungkuk, mencium pipi Abel yang tenang dalam gendonganku.
Pelan-pelan, Moana meraih tangan Henny dan menyelipkan sesuatu di genggamannya.
Henny cepat-cepat menahan, menggeleng keras. “Enggak, Mo. Nggak usah. Jangan kayak gini,” tolaknya sambil mencoba mengembalikan lembaran rupiah yang diberikan Moana.
“Ambil aja, Hen. Ini buat jajan anak-anak, bukan buat kamu,” Moana bersikeras, menutup jemari sahabatnya dengan penuh kasih.
Namun Henny tetap menggeleng. “Terima kasih, Mo. Tapi beneran nggak usah. Aku tahu biaya promil itu mahal banget. Simpanlah untukmu sendiri.”
Moana tersenyum kecil. “Aku masih ada kok kalau soal itu, Hen. Udah, jangan pikirin aku.”
Henny akhirnya tak banyak bicara lagi, hanya menatap sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. Moana lalu mencium pipiku, berbisik singkat, “Bye, Akira.”
Aku mengantarnya dengan senyum kecil, meski hati terasa nyeri. Aku dan Moana sama-sama tahu… Henny sedang berada di masa-masa sulit. Dua anak masih kecil, kebutuhan yang menumpuk, dan pekerjaan serabutan yang kadang hanya cukup untuk makan sehari-hari.
Sementara suaminya? Hanya pria mokondo, pemalas, bersandar pada istrinya, dengan pola pikir patriarki yang menyesakkan.
Aku mengantar Henny pulang ke rumahnya. Di jok belakang, Alan sudah terlelap. Abel pun kembali tertidur, wajah mungilnya tenang.
“Ra, boleh ngomong nggak?” suara Henny pelan, memecah keheningan di antara kami.
“Bolehlah. Ngomong aja.”
Ia menarik napas panjang sebelum melanjutkan. “Ra… jangan gara-gara liat keadaan rumah tanggaku, atau rumah tangga Moana, kamu jadi takut nikah, ya.”
Aku terdiam sejenak, lalu terkekeh singkat. “Aku cuma belum ketemu yang cocok aja, Hen.”
Henny mengangguk pelan, matanya menerawang ke jalan depan. “Kamu orang baik, Ra. Jodohmu pasti juga orang baik, hadiah yang Tuhan simpan untukmu.”
Aku tersenyum tipis. Tapi dalam hati, aku bergumam lirih, bukankah kau juga baik sekali, Hen? Lalu kenapa justru pria tak bertanggung jawab yang Tuhan pasangkan padamu?
“Menikah itu nggak seseram yang kau bayangkan kok, Ra,” katanya lagi, kali ini suaranya bergetar halus. “Asal ketemu yang tepat. Lebih baik terlambat menikah daripada menyesal setelah menikah sih."
Aku hanya diam. Tak tahu harus menjawab apa.
“Kayak aku gini, Ra… agak nyesel.” Bibirnya gemetar, tapi ia memaksa tersenyum. “Dapet suami yang kerjaannya cuma nonton TV, tidur, main HP. Aku kadang pengen pergi aja. Kadang juga ngerasa udah kayak orang gila. Pusing, bingung, mikirin suamiku.”
Aku menoleh sekilas ke arahnya. Sorot matanya terlihat lelah.
“Kenapa nggak pisah aja, Hen?” tanyaku hati-hati, meski kata-kata itu sudah lama kupendam. “Kalau pisah, kamu cuma tinggal mikirin anak-anak. Nggak perlu lagi capek mikirin pria mokondo begitu.”
Henny terdiam. Matanya menatap kosong ke arah jendela. “Aku nggak mau anak-anak kehilangan figur ayahnya, Ra,” jawab Henny lirih.
Aku menarik napas panjang, lalu menoleh padanya. “Hen, bukannya dari dulu anak-anak emang udah kehilangan sosok itu?” suaraku pelan, tapi tegas.
Ia menoleh singkat, wajahnya berubah. Aku melanjutkan, kata-kata yang selama ini kutahan akhirnya pecah begitu saja.
“Kalau anakmu nangis, dia ikut nenangin atau seenggaknya bantu gendong? Enggak kan, Hen? Kalau si kakak rewel, si adek juga lagi nangis, apa dia turun tangan bantu kamu? Enggak kan? Kalau susu si kecil habis, apa dia yang beliin? Enggak juga. Kamu sendiri yang harus kerja mati-matian demi anak-anakmu. Kamu sendiri yang berjuang.”
Suara di dalam mobil terasa semakin berat. Alan dan Abel tetap terlelap, kontras dengan ketegangan di antara kami.
“Hen…” aku menoleh padanya sebentar, dadaku terasa sesak. “Saat kamu sakit, dia bahkan masih tega minta kamu bikinin kopi. Pekerjaan rumah, semua tetap kamu yang tanggung. Jadi perannya apa? Untuk apa kamu tetap bertahan dengan orang seperti itu?”
Aku berhenti, menyadari nadaku meninggi. Sebenarnya aku tidak ingin menghakimi, tapi rasa peduli membuatku tak sanggup diam lebih lama.
Henny terdiam lama. Matanya berkaca-kaca, menatap keluar jendela seolah mencari jawaban di baliknya.
“Ra… dia memang nggak sempurna,” ucapnya akhirnya, suaranya bergetar. “Tapi dia tetap ayah dari anak-anakku.”
Aku menelan ludah, dadaku nyeri mendengarnya.
“Aku tahu dia sering bikin aku capek, bikin aku nangis, bikin aku bingung. Tapi… kalau dia nggak ada, aku takut makin berat. Aku takut anak-anakku nanti nanya… ‘Ayah ke mana?’ Lalu aku harus jawab apa?”
Ia mengusap air matanya cepat-cepat. Aku menatapnya, ingin membantah lagi, tapi lidahku kelu. Ada bagian dari dirinya yang begitu ingin percaya, percaya bahwa lelaki itu masih punya sisi baik, sekecil apapun.
“Kalau aku pergi, Ra ... Aku takut, aku takut nggak sanggup sendirian. Aku takut anak-anakku benar-benar kehilangan. Jadi… aku bertahan. Meski kadang rasanya udah nggak kuat.”
Air matanya jatuh lagi, tapi ia buru-buru menghapusnya. Kami diam setelah itu.
Aku... Akira, seorang manajer di perusahaan ternama, memang tidak pernah menaruh keinginan untuk menikah. Bagi sebagian orang, pernikahan adalah puncak bahagia. Tapi bagiku, pernikahan justru terdengar menakutkan.
Hari ini aku menemani sahabatku, Henny.
“Ooo, Sayang, sini sama Tante,” ucapku sambil meraih anak keduanya dari gendongan.
“Dia memang masih gampang rewel, Ra,” sahut Henny, sibuk mencari botol susu di dalam tas. Lega rasanya melihat si kecil perlahan tenang dalam gendonganku. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Suara tangisan lain tiba-tiba terdengar dari arah playground tempat makan ini.
Henny buru-buru bangkit, langkahnya tergesa menuju putra pertamanya yang tengah berebut mainan dengan anak pengunjung lain.
Aku hanya bisa memperhatikannya dari jauh, sambil menimang bayi mungil berusia delapan bulan yang kini terlelap di pelukanku. Setelah beberapa saat, Henny kembali. Senyum merekah di wajahnya saat melihat si kecil sudah tertidur pulas dalam gendonganku.
“Alan memang jarang main di playground, Ra. Makan di tempat seperti ini pun bisa dihitung dengan jari,” ujarnya lirih sambil menatap putra sulungnya yang sedang main prosotan.
Aku hanya mengangguk pelan, tanda bahwa aku mendengarnya.
“Oh, sini Abel. Takutnya kamu capek,” katanya seraya mengulurkan tangan meminta anak keduanya.
Aku menggeleng singkat. “Enggak apa-apa, biar Abel sama aku dulu. Kamu makan dulu gih.”
Senyum lembut kembali muncul di wajahnya. “Makasih ya, Ra.”
Aku balas tersenyum, lalu melangkah menuju area bermain. Mengawasi Alan dari jarak dekat, agar Henny bisa makan dengan tenang.
Ingatan lama tiba-tiba menyeruak, saat aku pernah mampir ke rumahnya beberapa bulan lalu. Hari itu, suara tangisan bayi menyambutku sejak di depan pintu. Hatiku langsung tercekat.
“Henny?” panggilku hati-hati, melangkah masuk.
Di ruang tengah, pemandangan itu membuat dadaku sesak. Makanan berserakan di lantai, Alan sibuk dengan mobil-mobilannya sambil sesekali menginjak nasi yang tumpah. Di sisi lain, Abel menangis kencang diatas kasur lantai.
Henny terduduk lemas di lantai, wajahnya pucat, matanya sembab. Begitu melihatku, bibirnya bergetar. “Akira…” suaranya lirih, sebelum akhirnya tangisnya pecah. Aku tak banyak bicara. Langsung menghampirinya dan memeluknya. Biarlah pelukan ini yang bicara.
Aku tahu, di Jakarta ini Henny tak punya siapa-siapa. Dia datang kesini ikut suaminya, tinggal di rumah kontrakan. Dulu, suaminya bekerja di salah satu pabrik. Dua tahun ini, dia tidak bekerja lagi. Itu yang kutahu dari cerita Henny.
Setelah tangis Henny agak reda, aku melepas pelukan perlahan.
“Botol susunya di mana, Hen? Mungkin si adek haus,” tanyaku pelan.
Henny menunduk, lalu menggeleng. Seketika seolah ada pisau menyayat dadaku. Tidak ada susu? Hatiku perih.
“Tunggu sebentar ya. Aku beliin sekarang. Susunya merk apa?” suaraku bergetar menahan panik.
“Apa saja, Ra. Yang penting untuk bayi enam bulan,” jawabnya pelan. Dia menatapku. "Makasih ya, Ra. Nanti kalau udah ada uang, kuganti."
Aku tersenyum lembut mengusap lengannya. "Nggak usah dipikirin," kataku.
Aku bergegas bangkit. Saat melintas di ruang samping, mataku sempat menangkap sosok suaminya. Duduk santai di sofa, menatap televisi dengan wajah datar, seakan hiruk-pikuk di rumah itu bukan apa-apa. Seolah tangisan bayi, tumpahan makanan, dan air mata istrinya hanyalah musik pengantar sore.
“Tante Akira, aku mau minum es boba,” suara Alan menyentakku dari lamunan.
“Baiklah, Sayang, tunggu sebentar di sini, ya,” jawabku sambil berdiri, lalu mengambilkan es boba di meja.
“Maaf, merepotkanmu lagi, Ra,” ucap Henny lembut, tatapannya penuh rasa bersalah.
Aku tersenyum tipis. “Enggak kok, Hen.”
Kuserahkan segelas es boba ke tangan mungil Alan. Anak itu langsung menyesapnya dengan semangat, pipinya mengembung lucu.
Tak lama, sosok yang familiar muncul dari arah pintu. Moana, sahabat kami yang lain. Wajahnya masih sama cantiknya seperti dulu saat kami SMA, seolah tak pernah kalah oleh waktu. Dulu ia primadona sekolah, dan entah bagaimana pesona itu masih melekat erat hingga kini.
“Hai, Henny! Aku kangen banget,” sapa Moana ceria, lalu mereka berpelukan singkat, cipika-cipiki hangat khas pertemuan perempuan.
Aku menghampiri mereka, Moana menoleh padaku. Tatapannya seketika melunak melihat Abel yang terlelap dalam gendonganku.
“Sini, Ra,” katanya pelan, kedua tangannya terulur hati-hati. “Biar aku aja yang gendong. Siapa tahu aku cepet dapat momongan,” suaranya gemetar di ujung kalimat.
Aku terdiam sejenak, lalu dengan perlahan menyerahkan Abel padanya. Moana meraihnya dengan penuh kelembutan, seolah bayi kecil itu adalah permata rapuh yang sudah lama ia nanti.
“Padahal kurasa aku udah cocok jadi ibu, ya kan, Ra?” bisiknya, matanya menerawang. “Tapi… entah kenapa Tuhan belum juga menitipkan.”
Aku tercekat. Tidak tahu harus merespons dengan kata apa. Tentang sabar, Moana sudah pasti paham. Tentang semangat, ia selalu juara dalam hal apapun.
Henny mengusap pelan lengan Moana, memberi dukungan tanpa kata. Aku tahu, sama sepertiku, ia juga tidak menemukan kalimat yang tepat.
“Untung kamu chat aku, Ra. Kalau enggak, mungkin aku sudah menangis sendirian di kamar," lanjut Moana lirih sambil menatap Abel di pelukannya. “Aku dan mertua… tadi pagi ikut acara syukuran empat bulanan tetangga satu RT,” suara Moana serak, matanya sudah berkaca-kaca. “Kalian tahu apa yang beliau katakan?”
Aku segera duduk di sampingnya, menatap penuh perhatian.
“Di depan banyak orang, mertuaku bilang aku perempuan nggak subur. Tanah gersang. Nggak bisa ngasih dia cucu.” Suaranya pecah, isakan lolos dari bibirnya. Air mata jatuh satu per satu, membasahi pipinya.
Aku refleks merangkul bahunya. Henny pun ikut mendekat, memeluk Moana dari sisi lain. Kami bertiga saling erat, seakan pelukan itu ingin mengatakan, kau tidak sendiri.
"Sakit banget rasanya," lirih Moana.
Moana adalah pejuang garis dua dalam usia pernikahannya yang menginjak 10 tahun.
“Orang kayak gitu musuhnya cuma lantai licin, Mo,” celetuk Henny, mencoba mencairkan suasana. “Mau aku beliin minyak bekas nggak, biar makin gampang kepleset?” godanya dengan wajah pura-pura serius.
Di sela-sela isaknya, bibir Moana akhirnya melengkung tipis. Senyum kecil itu, walau samar, jadi cahaya di antara luka.
“Eh, kamu pesen makanan dulu nggak sih,” kataku sambil menyodorkan buku menu ke arahnya. “Kalau lagi kesel, harus makan banyak, Mo. Anggap aja lagi ngunyah omongan mertua.”
Moana mengusap air matanya dengan tisu, kali ini senyumnya lebih lebar meski masih sembab. “Ya udah, aku mau makan yang banyak.”
Setelah selesai makan dan saling bercerita, Moana pamit pulang lebih dulu.
“Suamiku bentar lagi pulang kerja, aku cabut duluan ya,” katanya seraya meraih tasnya.
Aku dan Henny mengangguk.
“Mo, selama suamimu ada di pihakmu, dunia akan tetap baik-baik saja. Semangat, ya,” ujar Henny dengan senyum tulus.
Moana menatapnya, mengangguk pelan. “Iya… semoga dia selalu di pihakku. Kadang aku suka ketar-ketir, Hen. Takut suatu saat nanti dia lelah bareng aku, lalu termakan hasutan ibunya buat cari istri lagi.” Suaranya bergetar, ada cemas yang tak bisa disembunyikan.
“Aku yakin suamimu nggak akan begitu, Mo,” balas Henny lembut. “Semangat pupuk cinta kalian ya.”
“Semangat,” seru Moana, berusaha menguatkan dirinya sendiri. Ia lalu membungkuk, mencium pipi Abel yang tenang dalam gendonganku.
Pelan-pelan, Moana meraih tangan Henny dan menyelipkan sesuatu di genggamannya.
Henny cepat-cepat menahan, menggeleng keras. “Enggak, Mo. Nggak usah. Jangan kayak gini,” tolaknya sambil mencoba mengembalikan lembaran rupiah yang diberikan Moana.
“Ambil aja, Hen. Ini buat jajan anak-anak, bukan buat kamu,” Moana bersikeras, menutup jemari sahabatnya dengan penuh kasih.
Namun Henny tetap menggeleng. “Terima kasih, Mo. Tapi beneran nggak usah. Aku tahu biaya promil itu mahal banget. Simpanlah untukmu sendiri.”
Moana tersenyum kecil. “Aku masih ada kok kalau soal itu, Hen. Udah, jangan pikirin aku.”
Henny akhirnya tak banyak bicara lagi, hanya menatap sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. Moana lalu mencium pipiku, berbisik singkat, “Bye, Akira.”
Aku mengantarnya dengan senyum kecil, meski hati terasa nyeri. Aku dan Moana sama-sama tahu… Henny sedang berada di masa-masa sulit. Dua anak masih kecil, kebutuhan yang menumpuk, dan pekerjaan serabutan yang kadang hanya cukup untuk makan sehari-hari.
Sementara suaminya? Hanya pria mokondo, pemalas, bersandar pada istrinya, dengan pola pikir patriarki yang menyesakkan.
Aku mengantar Henny pulang ke rumahnya. Di jok belakang, Alan sudah terlelap. Abel pun kembali tertidur, wajah mungilnya tenang.
“Ra, boleh ngomong nggak?” suara Henny pelan, memecah keheningan di antara kami.
“Bolehlah. Ngomong aja.”
Ia menarik napas panjang sebelum melanjutkan. “Ra… jangan gara-gara liat keadaan rumah tanggaku, atau rumah tangga Moana, kamu jadi takut nikah, ya.”
Aku terdiam sejenak, lalu terkekeh singkat. “Aku cuma belum ketemu yang cocok aja, Hen.”
Henny mengangguk pelan, matanya menerawang ke jalan depan. “Kamu orang baik, Ra. Jodohmu pasti juga orang baik, hadiah yang Tuhan simpan untukmu.”
Aku tersenyum tipis. Tapi dalam hati, aku bergumam lirih, bukankah kau juga baik sekali, Hen? Lalu kenapa justru pria tak bertanggung jawab yang Tuhan pasangkan padamu?
“Menikah itu nggak seseram yang kau bayangkan kok, Ra,” katanya lagi, kali ini suaranya bergetar halus. “Asal ketemu yang tepat. Lebih baik terlambat menikah daripada menyesal setelah menikah sih."
Aku hanya diam. Tak tahu harus menjawab apa.
“Kayak aku gini, Ra… agak nyesel.” Bibirnya gemetar, tapi ia memaksa tersenyum. “Dapet suami yang kerjaannya cuma nonton TV, tidur, main HP. Aku kadang pengen pergi aja. Kadang juga ngerasa udah kayak orang gila. Pusing, bingung, mikirin suamiku.”
Aku menoleh sekilas ke arahnya. Sorot matanya terlihat lelah.
“Kenapa nggak pisah aja, Hen?” tanyaku hati-hati, meski kata-kata itu sudah lama kupendam. “Kalau pisah, kamu cuma tinggal mikirin anak-anak. Nggak perlu lagi capek mikirin pria mokondo begitu.”
Henny terdiam. Matanya menatap kosong ke arah jendela. “Aku nggak mau anak-anak kehilangan figur ayahnya, Ra,” jawab Henny lirih.
Aku menarik napas panjang, lalu menoleh padanya. “Hen, bukannya dari dulu anak-anak emang udah kehilangan sosok itu?” suaraku pelan, tapi tegas.
Ia menoleh singkat, wajahnya berubah. Aku melanjutkan, kata-kata yang selama ini kutahan akhirnya pecah begitu saja.
“Kalau anakmu nangis, dia ikut nenangin atau seenggaknya bantu gendong? Enggak kan, Hen? Kalau si kakak rewel, si adek juga lagi nangis, apa dia turun tangan bantu kamu? Enggak kan? Kalau susu si kecil habis, apa dia yang beliin? Enggak juga. Kamu sendiri yang harus kerja mati-matian demi anak-anakmu. Kamu sendiri yang berjuang.”
Suara di dalam mobil terasa semakin berat. Alan dan Abel tetap terlelap, kontras dengan ketegangan di antara kami.
“Hen…” aku menoleh padanya sebentar, dadaku terasa sesak. “Saat kamu sakit, dia bahkan masih tega minta kamu bikinin kopi. Pekerjaan rumah, semua tetap kamu yang tanggung. Jadi perannya apa? Untuk apa kamu tetap bertahan dengan orang seperti itu?”
Aku berhenti, menyadari nadaku meninggi. Sebenarnya aku tidak ingin menghakimi, tapi rasa peduli membuatku tak sanggup diam lebih lama.
Henny terdiam lama. Matanya berkaca-kaca, menatap keluar jendela seolah mencari jawaban di baliknya.
“Ra… dia memang nggak sempurna,” ucapnya akhirnya, suaranya bergetar. “Tapi dia tetap ayah dari anak-anakku.”
Aku menelan ludah, dadaku nyeri mendengarnya.
“Aku tahu dia sering bikin aku capek, bikin aku nangis, bikin aku bingung. Tapi… kalau dia nggak ada, aku takut makin berat. Aku takut anak-anakku nanti nanya… ‘Ayah ke mana?’ Lalu aku harus jawab apa?”
Ia mengusap air matanya cepat-cepat. Aku menatapnya, ingin membantah lagi, tapi lidahku kelu. Ada bagian dari dirinya yang begitu ingin percaya, percaya bahwa lelaki itu masih punya sisi baik, sekecil apapun.
“Kalau aku pergi, Ra ... Aku takut, aku takut nggak sanggup sendirian. Aku takut anak-anakku benar-benar kehilangan. Jadi… aku bertahan. Meski kadang rasanya udah nggak kuat.”
Air matanya jatuh lagi, tapi ia buru-buru menghapusnya. Kami diam setelah itu.
Other Stories
Di Bawah Langit Al-ihya
Tertulis kisah ini dengan melafazkan nama-Mu juga terbingkailah namanya. Berharap mega t ...
Broken Wings
Bermimpi menjadi seorang ballerina bukan hanya tentang gerakan indah, tapi juga tentang ke ...
Nestapa
Masa kecil Zaskia kurang bahagia, karena kedua orangtua memilih bercerai. Ayahnya langsung ...
Flower From Heaven
Setelah lulus SMA, Sekar Arum tidak melanjutkan kuliah seperti dua saudara kembarnya, Dyah ...
Mak Comblang Jatuh Cinta
“Miko!!” satu gumpalan kertas mendarat tepat di wajah Miko seiring teriakan nyaring ...
Mak Comblang Jatuh Cinta
Miko jatuh cinta pada sahabatnya sejak SD, Gladys. Namun, Gladys justru menyukai Vino, kak ...