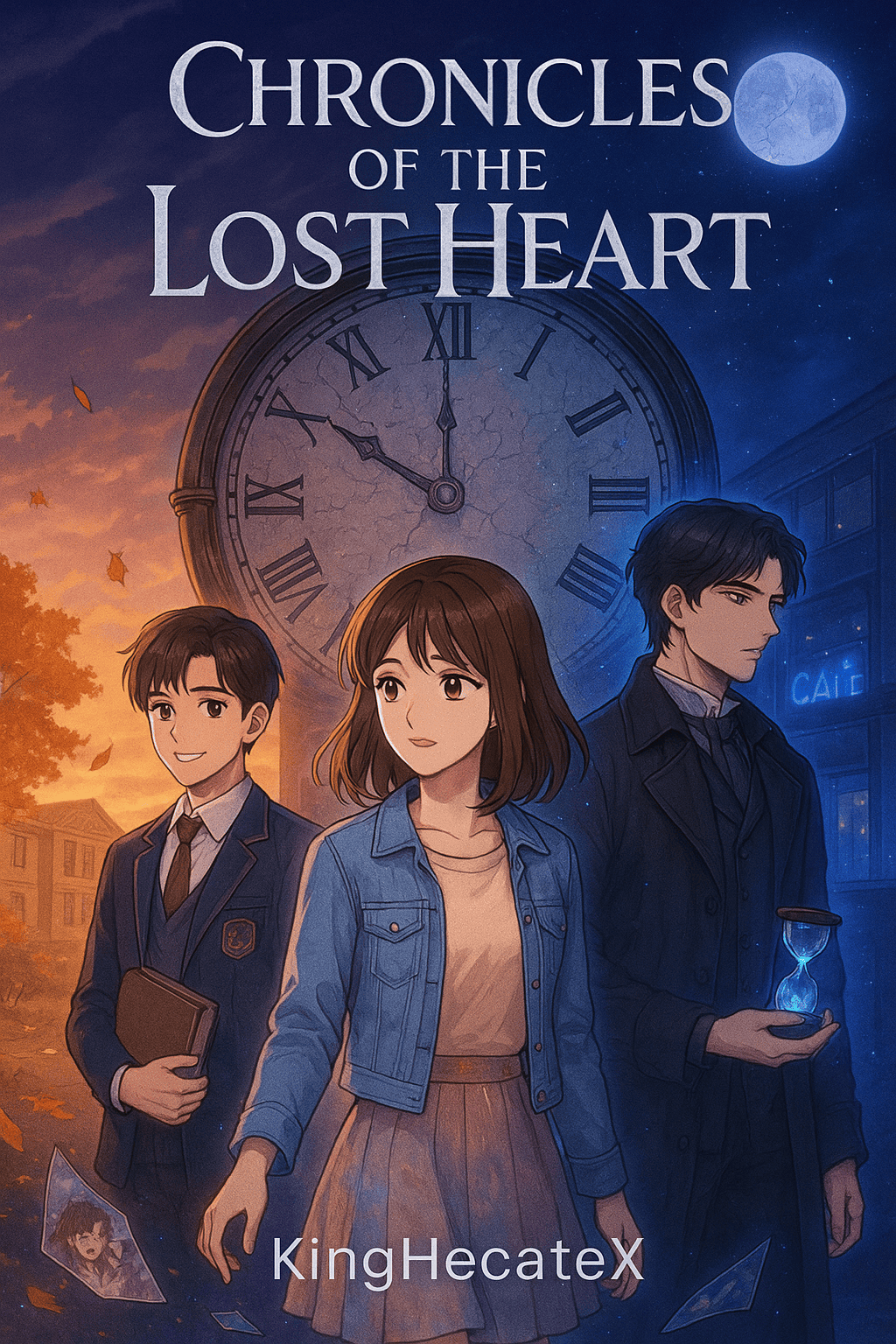Bab 1 – Kilas Balik: Ketika Segalanya Terlihat Sempurna
Setiap cerita memiliki titik awal. Cerita saya dimulai ketika segalanya terlihat sempurna. Empat anak yang begitu luar biasa. Yang tiga bersekolah dan bekerja di luar negeri sedangkan yang paling kecil 3 tahun menjadi penghibur yang sangat menggemaskan. Suami yang mempunyai latar belakang keluarga yang baik, mempunyai pekerjaan yang sangat mumpuni, pekerja keras, sangat bertanggung jawab, Bapak yang luar biasa buat anak-anak, sahabat dan partner terbaik dalam mengarungi kehidupan.
Saya tumbuh dalam keluarga yang mapan, dikenal luas di dunia bisnis dan sosial Jawa Barat. Selama lebih dari dua puluh tahun, saya mengabdikan diri di perusahaan keluarga hingga dipercaya memimpin sebagai CEO. Hidup saya dipenuhi pencapaian, rutinitas yang padat, dan peran besar dalam keluarga besar. Dari luar, segalanya tampak sempurna: rumah tangga harmonis, anak-anak yang berprestasi, dan karier yang stabil.
Namun di balik semua itu, ada kelelahan dan kebingungan yang jarang saya akui. Saya terlalu sibuk memenuhi ekspektasi orang lain, hingga lupa bertanya apa yang sebenarnya saya inginkan. Dan ketika badai datang, saya kehilangan segalanya dalam sekejap. Sebuah konflik bisnis yang seharusnya selesai secara perdata berubah menjadi kasus pidana. Vonis dijatuhkan, dan saya harus menerima kenyataan masuk ke dalam penjara.
Bagi saya, kehilangan terbesar bukan hanya kebebasan, harta, atau jabatan. Yang paling menghancurkan adalah runtuhnya kepercayaan: kepada sistem hukum, kepada orang-orang yang dulu saya percayai, bahkan kepada diri sendiri. Semua yang dulu saya anggap identitas—nama baik, kesuksesan, dan peran sosial—sirna begitu saja.
Tetapi justru dari kehancuran itu, perjalanan baru dimulai. Penjara menjadi pit stop—tempat perhentian paksa yang membuka ruang untuk merenung, bertanya ulang, dan menemukan siapa diri saya sebenarnya, di luar jabatan dan citra. Dari sinilah, proses transformasi itu dimulai.
Buku ini bukan tentang menyalahkan siapa-siapa. Ini tentang kejujuran—tentang melihat kembali hidup yang pernah saya jalani, kesalahan yang saya buat, dan bagaimana semuanya membawa saya ke pit stop terpenting dalam hidup saya.
Awal Perjalanan
Pernahkah kamu merasa dunia terlalu cepat berlari, dan kamu mulai kehilangan arah? Hidup saya berubah bukan karena saya kalah, tetapi karena saya berhenti untuk terlalu percaya dan mulai berkonsentrasi kepada keluarga kecil saya yang selama ini menjadi prioritas kesekian setelah keluarga besar dan perusahaan.
Setiap pagi, kita bangun dengan harapan bahwa hari ini akan membawa kebahagiaan dan mendekatkan kita pada cita-cita. Para pelajar berharap bertemu teman-teman di sekolah, mendapatkan nilai baik, dan naik kelas. Para pekerja berharap menyelesaikan tugas dengan baik, mendapat apresiasi, dan meraih kenaikan karir. Pasangan yang baru menikah berharap segera dikaruniai keturunan dan kehidupan yang harmonis.
Namun, dalam kehidupan yang serba instan ini, dengan begitu banyak harapan dan target, kita seakan-akan hidup dalam perlombaan F1. Semua fokus pada tujuan masing-masing, menginjak pedal sedalam-dalamnya, berlomba mencapai garis finish yang tidak terlihat dan kadang tidak ada batasnya.
Media sosial memperburuk keadaan. Dari Facebook, Path, Instagram, hingga TikTok, semua berlomba untuk terlihat lebih baik, lebih kaya, lebih cantik, lebih sukses. Banyak orang, terutama Gen Z, Milenial, dan Gen Alpha, sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang sekadar konten pencitraan atau gimmick penjualan.
Kita menjadi takut untuk “berhenti sebentar” guna mensyukuri pencapaian, mengasah kemampuan, atau menyusun ulang strategi. Padahal, dalam dunia balap F1, setiap kendaraan hebat sekalipun membutuhkan Pit Stop—sebuah jeda singkat namun krusial untuk memperbaiki, mengganti, dan memulihkan. Tanpa henti sejenak itu, mustahil kendaraan bisa melaju maksimal hingga garis akhir.
Saya pun begitu. Dulu, saya bangun pagi bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk terus menaklukkan target-target besar. Seolah-olah dunia menunggu saya untuk menaklukkannya. Namun, seiring berjalannya waktu, saya mulai menyadari bahwa ekspektasi-ekspektasi itu menambah berat beban saya. Lelah berlari tanpa tahu kapan harus berhenti. Saya mulai kehilangan arah.
Ketika hidup tampak sempurna di luar, diam-diam badai bisa datang dari arah yang tidak terduga. Keyakinan terhadap sistem hukum, relasi bisnis, bahkan kepada orang-orang yang dulu saya percayai sepenuh hati, perlahan-lahan mulai retak. Saya tidak kalah karena tidak berjuang, tapi karena saya dipaksa berhenti oleh sistem yang semestinya melindungi, namun justru mencederai.
Saat berurusan dengan hukum, entah kita bersalah, tidak bersalah, atau merasa tidak bersalah, kita dihadapkan pada “tempat” terburuk yang tak pernah terlintas dalam benak. Apapun latar belakang kita, pendidikan, agama, saat pertama pintu jeruji ditutup dengan kita di dalamnya, kita berhadapan dengan perasaan tergelap yang pernah dirasakan. Semua rencana, harapan, asa seakan terenggut. Kita seakan masuk ke dalam lubang gelap yang tak tahu dasarnya.
Beberapa hari pertama hidup di penjara terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Tembok tinggi, jeruji besi, dan suara pintu besi yang dibanting setiap kali terkunci menjadi irama baru yang harus saya terima, meski hati menolak. Rasanya absurd—baru kemarin saya rapat direksi di ruang berpendingin, membahas strategi bisnis, dan kini saya tidur di lantai dingin, berbagi ruang sempit dengan orang-orang asing. Pikiran saya kacau, hati saya marah, dan tubuh saya menolak kenyataan. Yang paling sulit adalah menjelaskan kepada diri sendiri bahwa ini nyata, bahwa saya sedang menjalani hari-hari yang tak pernah saya bayangkan akan terjadi dalam hidup saya.
Di awal masa tahanan, saya ditempatkan di ruangan bersama delapan orang tahanan lainnya. Perasaan takut, sedih, kecewa, marah, dendam, malu, bingung bercampur aduk. Ruang tahanan yang kelam dan sumpek serta keluh kesah dari tahanan lain menambah kuat semua perasaan negatif.
Pada titik itu, saya belajar bahwa yang paling menyakitkan bukan hanya kehilangan kebebasan, tetapi kehilangan kepercayaan terhadap keadilan. Tidak ada tempat untuk menyangkal atau membela diri secara lantang—semuanya telah diputuskan. Saya tenggelam dalam kemarahan dan rasa tidak terima.
Di atas semua itu, ketidakpastian dan ketidakberdayaan atas masa depan mendominasi. Hidup yang selama ini tertata dengan target, planning jangka pendek dan panjang, jadwal harian pekerjaan, keluarga, dan anak, tiba-tiba terenggut. Jangankan mengontrol jadwal, mengetahui jam saat itu saja hanya adzan dan waktu kontrol petugas yang menjadi penanda waktu.
Dalam kehancuran itu, saya mulai belajar memahami apa yang dahulu sering saya dengar, tapi belum saya hayati sepenuh hati.
“Katakanlah: Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki…” (QS. Ali ‘Imran: 26).
Ayat ini tiba-tiba menjadi sangat nyata. Bahwa sehebat apa pun manusia merancang dan menjaga, jika Allah berkehendak mencabut, maka semuanya bisa hilang dalam sekejap. Dan jika Allah ingin meninggikan kembali, maka tak ada yang bisa menghalangi-Nya.
Di ruang sempit ini, saya akan menemukan ruang paling luas: ruang untuk mengubah diri. Pit Stop saya adalah Lembaga Pemasyarakatan .. Penjara.
Other Stories
Suara Dari Langit
Apei tulus mencintai Nola meski ditentang keluarganya. Tragedi demi tragedi menimpa, terma ...
Chronicles Of The Lost Heart
Ketika seorang penulis novel gagal menemukan akhir bahagia dalam hidupnya sendiri, sebuah ...
Puzzle
Ros yatim piatu sejak 14 tahun, lalu menikah di usia 22 tapi sering mendapat kekerasan hin ...
Wajah Tak Dikenal
Ketika Mahesa mengungkapkan bahwa ia mengidap prosopagnosia, ketidakmampuan mengenali waja ...
Cinta Buta
Marthy jatuh cinta pada Edo yang dikenalnya lewat media sosial dan rela berkorban meski be ...
Rindu Yang Tumbuh Jadi Monster
Adrian nggak pernah nyangka, jatuh cinta bisa berawal dari hal sesederhana ngeliat cewek n ...