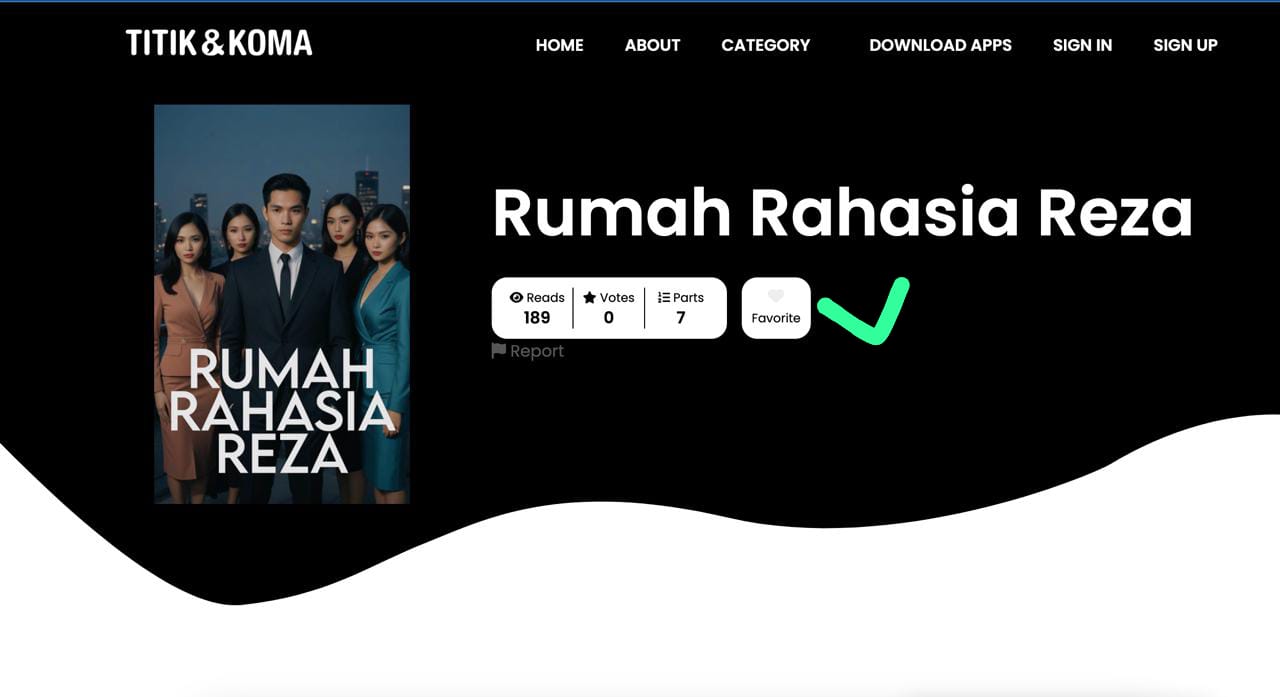Bab 4 - Pembicaraan Serius
Sari mengangguk pasrah. Bukan berarti setuju, dia hanya berpikir, jika mendebat Bu Dewi saat ini hanya percuma. Dia dan majikannya sama-sama dalam keadaan lelah. Mungkin besok, sebelum membuka warung, Bu Dewi masih bisa diajak bicara.
Sepeninggal Bu Dewi, Sari tersenyum sendiri. Terkadang dia masih kaget, sekaligus kagum pada dirinya sendiri. Dahulu dia selalu bicara frontal terhadap siapa pun, tetapi kini bisa sedikit mengerem sambil melihat kondisi.
Sari menyeberang jalan. Menghampiri Raka yang sudah bersiap. "Raka, ayo kita pulang."
“Wih, banyak juga ya, Mak.” Raka menunjuk kresek hitam yang dibawa Sari. Dia tahu betul itu bungkusan nasi sisa yang berhasil mamaknya kumpulkan sedari siang. “Besok dibikin nasi goreng ya, Mak, bosen makan bubur terus.”
Sari menelan ludah.
Bubur yang dimaksud Raka adalah nasi sisa yang dia rebus dengan sedikit air, dan diberi satu bungkus penyedap rasa. Menu andalan untuk mengisi perut setiap pagi.
Jangan tanya enak atau tidak. Bagi mereka berdua, dapat mengisi perut setiap hari merupakan sebuah anugerah besar.
“Pakai bumbu instan saja, Mak. Ada tuh bumbu nasi goreng yang seribuan,” kata Raka lagi.
“Coba nanti masih ada uang sisa buat beli minyak atau nggak ya,” sahut Sari. Mencoba tersenyum.
“Tadi aku dapat lima belas ribu, Mak. Cukup kalau buat beli minyak segelas.” Raka bersikeras. Lalu dia menepuk karung yang dia panggul. “Nih, besok pasti kita dapat lebih. Tadi aku dapat kardus manyan banyak.”
“Jangan, itu uang kamu tabung saja. Buat nambahin biaya masuk SMP.”
Raka mendengkus pelan. “Mak, aku lulus SD saja nggak apa-apa, nggak usah sekolah lagi. Yang penting aku sudah bisa baca, sudah bisa nulis. Aku mau kerja saja, Mak.”
“Kerja apa?” Sari menoleh. Memperlihatkan wajah jenaka. Alisnya terjungkit separuh.
“Ya, apa saja kan bisa, Mak. Cuci mobil di bengkel Koh Cencen, atau buruh panggul di toko Pak Haji.” Nada suara Raka mantap. “Bang Beben katanya dari kelas lima kerja sama Pak Haji, Mak. Sampai sekarang.”
Sari tertawa. “Terus?”
“Kok terus? Ya aku mau kerja gitu, Mak.”
“Kamu mau kayak Bang Beben juga? Selamanya kerja kayak gitu? Sampai kamu tua… terus nanti kamu nikah, anakmu juga hanya lulus SD, dan jadi buruh panggul juga. Mau begitu?”
Raka spontan berhenti. Mengernyit.
Sari sadar, berbicara tentang pernikahan dengan anak dua belas tahun itu adalah hal yang sedikit aneh. Namun kenyataannya, dia melahirkan Raka di usia yang tidak jauh dari usia anaknya sekarang.
“Nanti di rumah, Mamak mau cerita serius boleh?” tanya Sari.
“Soal pekerjaan ya, Mak?” Raka balik bertanya dengan polos.
Sari mengangguk.
Tanpa dikomando, langkah kaki Sari dan Raka membelok ke sebuah warung kecil. Tadi pagi, mereka sudah menitipkan tabung gas di situ.
Pemilik warung pun seakan tahu. Begitu melihat kedatangan Sari, dia segera keluar sembari menenteng tabung gas.
“Apa nggak kasihan anakmu, Sar? Masih kecil diajak kerja di warung makan sampai malam, mana yang makan di situ kebanyakan supir-supir dan laki-laki jalanan nggak jelas.” Si pemilik warung berkomentar.
“Aku nggak kerja di situ,” tukas Raka sengit. Tampak tidak terima.
“Hmm, tuh kan kamu jadi anak nakal. Seringnya gaul sama sopir-sopir sih. Paling sebentar lagi jadi kernet,” sahut pemilik warung tidak mau kalah.
Raka terjengit. “Emang kenapa jadi kernet? Kan halal—”
“Raka… sudah, Nak,” potong Sari. Tangannya merogoh saku daster. “Kalau sama minyak goreng gelas, teh celup saset, dan bumbu instan nasi goreng berapa, Bu?”
Pemilik warung berpikir sejenak sebelum menyebutkan nominal.
Dan Sari lega mengetahui uangnya cukup. Dia pun mengulurkan uang pas.
“Ajarin anakmu sopan santun, Sar!” Pemilik warung menerima uang Sari, lalu mengambil barang-barang yang telah disebutkan tadi.
Sari diam saja. Perempuan cantik tirus itu hanya mengucapkan terima kasih saat menerima belanjaannya. “Ayo, Ka.”
“Miskin, belagu,” desis pemilik warung tersebut. Dia kesal karena merasa diabaikan.
Sari menoleh pada Raka. Kentara sekali anaknya itu menahan amarah.
“Nah, itu contohnya kalau kamu hanya mau tamat SD saja, Ka,” ujar Sari. “Kita akan terus miskin, dihina dan direndahkan. Jujur sama Mamak, pasti kamu pengen ngamuk kan?”
“Hehe iya, pengen rasanya aku tabok mulutnya itu, Mak. Sudah sering dia gitu, ibu-ibu kok mem-bully anak-anak,” geram Raka sepenuh hati.
“Sari! Rumahmu mbok ya jangan digelapin gitu, lingkungan sini jadi serem.”
Sari dan Raka otomatis menoleh. Seorang ibu di depan teras rumahnya menatap mereka dengan pandangan tidak enak.
“Kerja sampai malam kok nggak kuat beli token listrik. Yang dua puluh lima loh ada, utang dulu di toko….”
“Yuk jalan lebih cepat, Ka,” bisik Sari.
Raka menyeringai.
“Heh, Sari!” Si Ibu menjadi geram saat melihat Sari mempercepat langkah. Demikian juga dengan Raka. “Aku sumpahin budek beneran kalian berdua. Miskin aja sombong!”
Sepeninggal Bu Dewi, Sari tersenyum sendiri. Terkadang dia masih kaget, sekaligus kagum pada dirinya sendiri. Dahulu dia selalu bicara frontal terhadap siapa pun, tetapi kini bisa sedikit mengerem sambil melihat kondisi.
Sari menyeberang jalan. Menghampiri Raka yang sudah bersiap. "Raka, ayo kita pulang."
“Wih, banyak juga ya, Mak.” Raka menunjuk kresek hitam yang dibawa Sari. Dia tahu betul itu bungkusan nasi sisa yang berhasil mamaknya kumpulkan sedari siang. “Besok dibikin nasi goreng ya, Mak, bosen makan bubur terus.”
Sari menelan ludah.
Bubur yang dimaksud Raka adalah nasi sisa yang dia rebus dengan sedikit air, dan diberi satu bungkus penyedap rasa. Menu andalan untuk mengisi perut setiap pagi.
Jangan tanya enak atau tidak. Bagi mereka berdua, dapat mengisi perut setiap hari merupakan sebuah anugerah besar.
“Pakai bumbu instan saja, Mak. Ada tuh bumbu nasi goreng yang seribuan,” kata Raka lagi.
“Coba nanti masih ada uang sisa buat beli minyak atau nggak ya,” sahut Sari. Mencoba tersenyum.
“Tadi aku dapat lima belas ribu, Mak. Cukup kalau buat beli minyak segelas.” Raka bersikeras. Lalu dia menepuk karung yang dia panggul. “Nih, besok pasti kita dapat lebih. Tadi aku dapat kardus manyan banyak.”
“Jangan, itu uang kamu tabung saja. Buat nambahin biaya masuk SMP.”
Raka mendengkus pelan. “Mak, aku lulus SD saja nggak apa-apa, nggak usah sekolah lagi. Yang penting aku sudah bisa baca, sudah bisa nulis. Aku mau kerja saja, Mak.”
“Kerja apa?” Sari menoleh. Memperlihatkan wajah jenaka. Alisnya terjungkit separuh.
“Ya, apa saja kan bisa, Mak. Cuci mobil di bengkel Koh Cencen, atau buruh panggul di toko Pak Haji.” Nada suara Raka mantap. “Bang Beben katanya dari kelas lima kerja sama Pak Haji, Mak. Sampai sekarang.”
Sari tertawa. “Terus?”
“Kok terus? Ya aku mau kerja gitu, Mak.”
“Kamu mau kayak Bang Beben juga? Selamanya kerja kayak gitu? Sampai kamu tua… terus nanti kamu nikah, anakmu juga hanya lulus SD, dan jadi buruh panggul juga. Mau begitu?”
Raka spontan berhenti. Mengernyit.
Sari sadar, berbicara tentang pernikahan dengan anak dua belas tahun itu adalah hal yang sedikit aneh. Namun kenyataannya, dia melahirkan Raka di usia yang tidak jauh dari usia anaknya sekarang.
“Nanti di rumah, Mamak mau cerita serius boleh?” tanya Sari.
“Soal pekerjaan ya, Mak?” Raka balik bertanya dengan polos.
Sari mengangguk.
Tanpa dikomando, langkah kaki Sari dan Raka membelok ke sebuah warung kecil. Tadi pagi, mereka sudah menitipkan tabung gas di situ.
Pemilik warung pun seakan tahu. Begitu melihat kedatangan Sari, dia segera keluar sembari menenteng tabung gas.
“Apa nggak kasihan anakmu, Sar? Masih kecil diajak kerja di warung makan sampai malam, mana yang makan di situ kebanyakan supir-supir dan laki-laki jalanan nggak jelas.” Si pemilik warung berkomentar.
“Aku nggak kerja di situ,” tukas Raka sengit. Tampak tidak terima.
“Hmm, tuh kan kamu jadi anak nakal. Seringnya gaul sama sopir-sopir sih. Paling sebentar lagi jadi kernet,” sahut pemilik warung tidak mau kalah.
Raka terjengit. “Emang kenapa jadi kernet? Kan halal—”
“Raka… sudah, Nak,” potong Sari. Tangannya merogoh saku daster. “Kalau sama minyak goreng gelas, teh celup saset, dan bumbu instan nasi goreng berapa, Bu?”
Pemilik warung berpikir sejenak sebelum menyebutkan nominal.
Dan Sari lega mengetahui uangnya cukup. Dia pun mengulurkan uang pas.
“Ajarin anakmu sopan santun, Sar!” Pemilik warung menerima uang Sari, lalu mengambil barang-barang yang telah disebutkan tadi.
Sari diam saja. Perempuan cantik tirus itu hanya mengucapkan terima kasih saat menerima belanjaannya. “Ayo, Ka.”
“Miskin, belagu,” desis pemilik warung tersebut. Dia kesal karena merasa diabaikan.
Sari menoleh pada Raka. Kentara sekali anaknya itu menahan amarah.
“Nah, itu contohnya kalau kamu hanya mau tamat SD saja, Ka,” ujar Sari. “Kita akan terus miskin, dihina dan direndahkan. Jujur sama Mamak, pasti kamu pengen ngamuk kan?”
“Hehe iya, pengen rasanya aku tabok mulutnya itu, Mak. Sudah sering dia gitu, ibu-ibu kok mem-bully anak-anak,” geram Raka sepenuh hati.
“Sari! Rumahmu mbok ya jangan digelapin gitu, lingkungan sini jadi serem.”
Sari dan Raka otomatis menoleh. Seorang ibu di depan teras rumahnya menatap mereka dengan pandangan tidak enak.
“Kerja sampai malam kok nggak kuat beli token listrik. Yang dua puluh lima loh ada, utang dulu di toko….”
“Yuk jalan lebih cepat, Ka,” bisik Sari.
Raka menyeringai.
“Heh, Sari!” Si Ibu menjadi geram saat melihat Sari mempercepat langkah. Demikian juga dengan Raka. “Aku sumpahin budek beneran kalian berdua. Miskin aja sombong!”
Other Stories
Akibat Salah Gaul
Nien, gadis desa penerima beasiswa di sekolah elite Jakarta, kerap dibully hingga dihadapk ...
Hopeless Cries
Merasa kesepian, tetapi sama sekali tidak menginginkan kehadiran seseorang untuk menemanin ...
Keluarga Baru
Surya masih belum bisa memaafkan ayahnya karena telah meninggalkannya sejak kecil, disaat ...
Cinta Harus Bahagia
Seorang kakak yang harus membesarkan adiknya karena kematian mendadak kedua orangtuanya, b ...
Kado Dari Dunia Lain
"Jika Kebahagiaan itu bisa dibeli, maka aku akan membelinya." Di tengah kondisi hidup Yur ...
Percobaan
percobaan ...