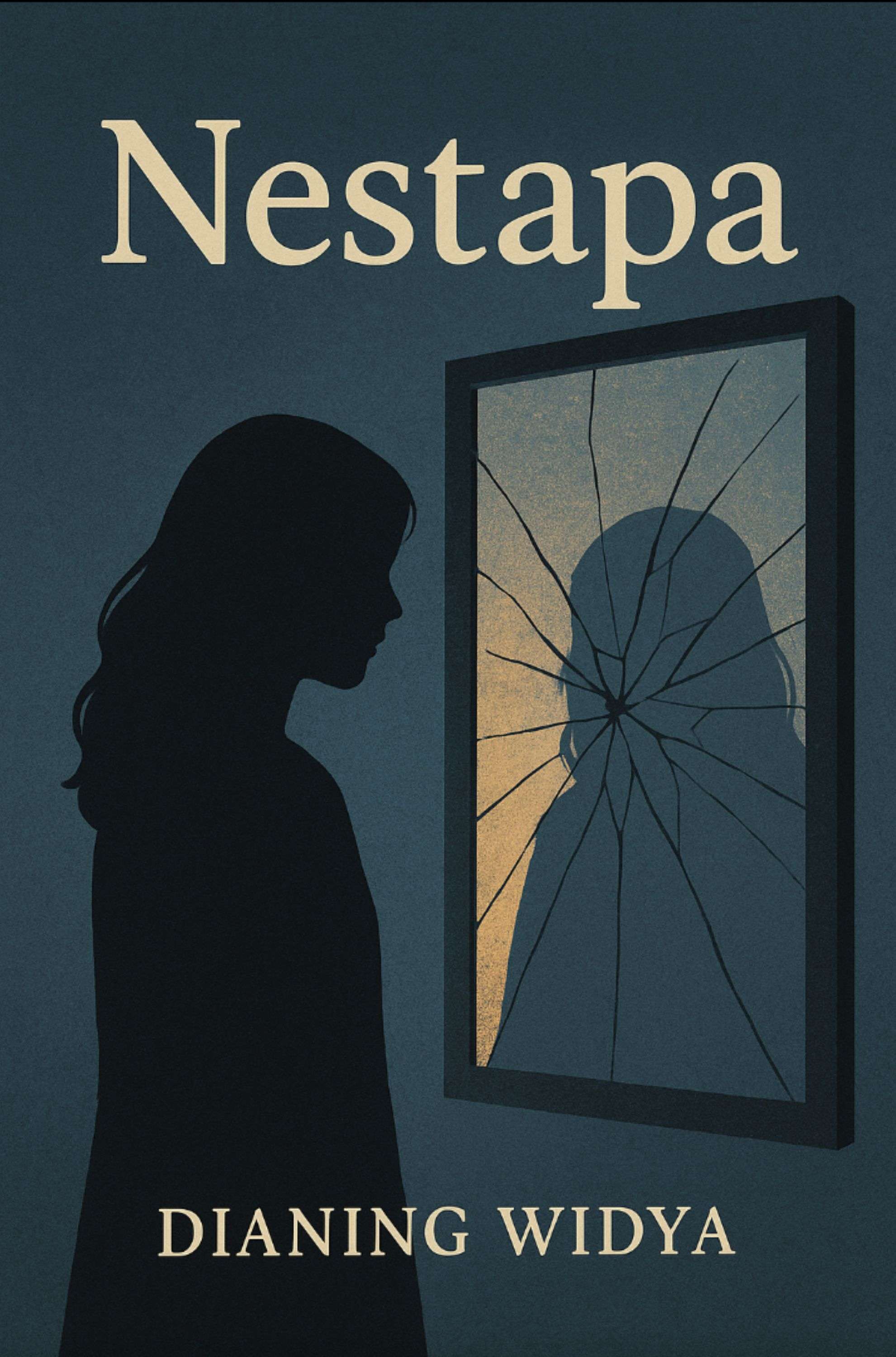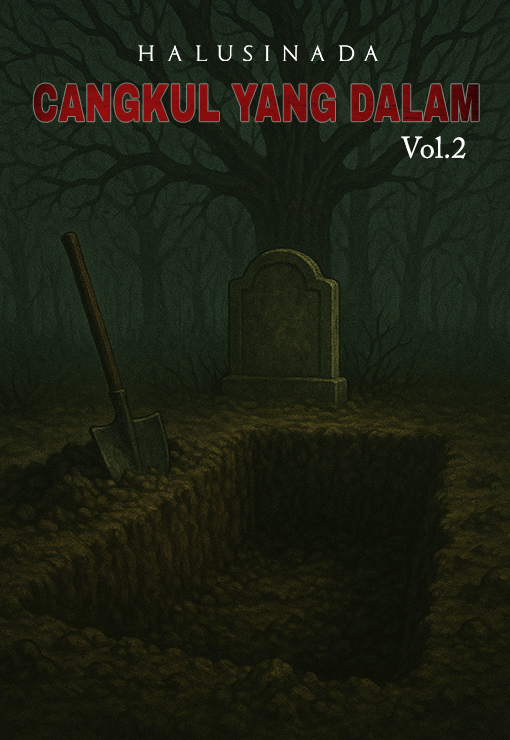10. Keputusan Tersulit
Memagut rindu pada ribuan malam, akhirnya terbayarkan lewat pancaran yang ia sunggingkan kepadaku. Teresa telah mengembalikan kembali kepercayaanku akan cinta kami. Membuatku mampu menegakkan kepala saat kembali pulang ke tanah air lalu memperlihatkan pada mereka yang telah menaruh iba pada seorang aku. Inilah kekasihku, dan kami akan segera menunaikan janji suci yang sempat terendap begitu lama.
Namun satu keresahan berlalu, kini tergantikankan oleh keresahan yang lain. Aku tak menutup mata bagaimana air muka Nadya saat menyadari Teresa tepat berada di sampingku. Ia tersenyum, namun aku tahu hatinya menangis. Sungguh, pasca hari itu aku ingin sekali berbicara empat mata dengannya, namun sepertinya ia menolak dengan alasan tak ingin merusak hubunganku dengan Teresa. Nadya tak menyadari, ada sebentuk luka baru yang tergores di hatiku.
Aku berdiri mantap di lokasi proyek perumahan di Kampung Alor. Kuhela napas panjang. Lega rasanya saat semua urusanku berhasil kuselesaikan. Proyek kerja sama ini hampir rampung 75 persen, dan untuk menyelesaikan sisa dari pekerjaan itu aku tak perlu sesibuk kemarin. Seminggu yang lalu Pak Andre telah menyusun rencana proyek lain untukku di Jakarta, ia berharap aku bisa menyelesaikan sisa pekerjaan ini dan kembali ke Magellan Realty sesegera mungkin. Syukurlah, aku mampu membayar lunas setelah kinerjaku yang memburuk beberapa bulan yang lalu. Kupikir meninggalkan Dili dalam waktu satu bulan ini tidak ada salahnya, toh pekerjaan yang tersisa adalah bagiannya Carlos. Yang perlu kulakukan hanyalah tetap menjalin komunikasi via telepon atau email sekedar koordinasi.
Getaran ponsel membuyarkan lamunanku. Biasanya di sela-sela pekerjaan ini, Nadya selalu menghubungi menanyakan apakah aku sudah makan siang atau belum. Namun semenjak Teresa kembali, ia seolah melupakan kebiasaannya.
“Halo?” ujarku seraya melangkah menjauh dari lokasi proyek.
“Halo? Halo? Sayang, kok berisik banget sih? Kamu lagi ada di mana?”
“Aku lagi di lokasi proyek,” jawabku dengan suara setengah berteriak.
“Mau makan siang bareng gak?”
Aku memperhatikan Alexandre Christie yang melingkar di pergelangan tangan. Pukul setengah satu siang. Masih ada waktu sepertinya buat pergi makan dengan kekasihku. “Mau. Emang kita makan di mana?” responsku beberapa saat kemudian.
“Kita makan ikan bakar aja di Pantai Kelapa, mau? Kebetulan aku lagi deket daerah situ bareng Anthony.”
Degg! Nama itu. Nama yang sempat membuat perasaanku tidak nyaman selama beberapa hari ke belakang. “Maksud kamu kita makan bertiga?” tebakku sinis.
“Halo? Apa? Gak kedengeran?”
Aku menggelengkan kepala. Sudahlah, aku tak perlu memelihara rasa cemburu berlebihan seperti ini. “Gak apa-apa kok. Ya udah aku ke sana setengah jam lagi ya,” ujarku dengan volume suara yang lebih keras.
Bibirku tetap tersungging seakan meyakinkan diri bahwa tak ada yang Teresa sembunyikan tentang Anthony. Meski aku tak menutup mata ada sebentuk rasa simpati dari caranya menatap Teresa, dan si bodoh itu seakan tak bersalah ketika aku dengan jelas ada di sampingnya.
“Teresa sering membicarakanmu, kamu seharusnya bahagia memiliki kekasih seperti dia,” komentar lelaki itu saat kami berkenalan tempo hari. Kami hanya berdua di dalam pick up milik Anthony, menunggu Teresa membeli minuman ringan di sebuah minimarket.
Yes, I am! Tentu saja bodoh! umpatku dalam hati. Kalimatnya terdengar menyudutkan seolah aku telah menerlantarkannya. “Aku lelaki paling beruntung di dunia ini,” timpalku.
“Ya. Seharusnya seperti itu.”
Seketika aku menoleh. “Maaf, bukan seharusnya. Tapi memang aku bangga memilikinya!” tegasku. Entah kenapa aku merasa Anthony tidak menyukaiku.
“Maaf kawan, aku tidak bermaksud menyinggungmu. Ya, aku bisa melihat dari raut wajahmu. Tak mungkin wanita sehebat Teresa kamu lepaskan begitu saja,” dan senyuman itu tetap saja menyisakan aura sinis yang ia tujukan padaku.
***
Matahari tepat berada di atas kepala, namun cukup teduh dengan hembusan angin dari arah pantai. Setelah beberapa saat akhirnya aku menemukan kedai tempat janjian makan siang kami. Dari jarak sepuluh meter, dengan mudah bisa kutangkap bayangan kekasihku di antara kelompok meja yang tersusun rapi di teras kedai. Lagi-lagi langkahku tertahan saat melihat keakraban dua anak manusia itu. Siapapun setuju, mereka seperti pasangan kekasih. Sialan! Kenapa sulit sekali mengenyahkan pikiran buruk ini? Kuhela napas sekali lagi lalu bergegas menghampiri mereka, menghindari berbagai prasangka yang semakin membuatku gila.
“Hai… sepertinya aku terlambat.”
“Hei sayang!” Teresa menyambutku dengan penuh suka cita. “Nggak kok, ini makanan sudah aku pesan sejak tadi. Jadi makanan sudah siap pas kamu dateng,” ujarnya seraya mempersilakanku duduk di sampingnya. Sementara Anthony masih tersenyum memperhatikan kemesraan kami.
“Apa kabar Bro?” sapaku sekedar basa-basi.
“Yup. Aku baik. Kamu tidak keberatan kan aku ikut makan siang bersama kalian?”
“Why not? Bukannya kalian sudah jalan bareng sejak tadi? Masa iya kamu pergi gitu aja. Kamu adalah kawan baik Teresa, itu berarti kawan baikku pula,” ujarku bermulut manis.
“Syukurlah. Tadinya aku khawatir kamu berpikiran macam-macam soal kami,” kali ini aku terdiam. Lelaki ini terlalu banyak bicara. Seandainya Teresa tidak ada di sampingku. Mungkin sudah kuhajar mulutnya itu.
“Oh iya, perempuan yang sempat tinggal di hotelmu, siapa namanya? Dia baik-baik aja kan?”
Aku mengepal jemariku menahan marah. Sepertinya dia ingin mengadu domba soal keberadaan Nadya tempo hari di hotelku. “Nadya maksudmu? Dia tidak tinggal di sana. Kebetulan dia sedang main ke tempatku. Nadya itu sahabat Teresa. Masa Teresa tidak cerita apa-apa tentang Nadya? Kamu gak cerita soal Nadya ke Anthony, Sayang?” tanyaku pada Teresa. Mungkin ini seperti pembelaan diri, karena aku merasa lelaki itu ingin menyerangku di segala sisi.
“Belum. Lagian buat apa aku cerita soal Nadya ke Anthony?” Teresa sendiri terlihat bingung dengan arah pembicaraan kami. “Cuma anehnya, kapan kamu ketemu Nadya? Perasaan, aku baru sekali kenalin dia pas masih di Jakarta.”
Hening. Aku merasa seperti diinterogasi oleh dua orang ini. “Teresa, kamu gak mikir macem-macem kan?” merasa kesal sendiri, aku menjatuhkan kembali sendok dan garpu ke meja.
Teresa tahu mood-ku menjadi memburuk. “Nggak. Hm… udah ah lupain aja. Kok jadi tegang gini. Ayo kita makan. Kamu bukannya mau cepet balik ke kantor?” ujar Teresa kikuk.
***
Benar juga, kekesalan ini masih berlanjut sampai aku tiba di rumah. Rasanya ingin meluapkan semua amarah ini. Tapi pada siapa? Nadya? Teresa? Ah justru dua perempuan itu yang membuat kepalaku merasa pening seperti ini.
“Udahlah Bro, gak usah dimasukin hati. Emang kayak gitu kali karakter si Anthony. Mulutnya pedas kayak perempuan. Masih ada yang lebih layak lo pikirin,” pada akhirnya aku mengadu pada Restu via ponsel. Lelaki itu mengetahui segala hal yang terjadi padaku selama di Dili. Tentang kesiapan aku melangkah bersama Teresa dan kemantapan aku ninggalin Nadya.”
“Gue gak berkutik, Res. Satu sisi gue bahagia Teresa kembali, tapi satu sisi gak bisa dipungkiri hati gue separuhnya menjadi milik Nadya.”
“Elo main api sih, ya seperti ini jadinya. Segera selesaikan sebelum semua terlanjur jauh. Jangan hancurkan rencana yang udah lo buat bertahun-tahun hanya karena sebuah affair yang seumur jagung. Gue yakin Nadya mengerti. Dia tentunya masih punya nalar kan?”
“Seperti yang kita tahu, cinta kadang tak punya logika, right?” ujarku sinis.
“Whatever… tapi yang musti lo sadari. Apa tujuan lo menapaki ranah Timor Leste? Teresa, bukan?”
“Iya,” jawabku pendek.
“Nah itu. Inget sobat, merusak kebahagiaan lebih mudah daripada membangun kebahagiaan itu sendiri. Masa lo mau menghancurkan kebahagiaan yang selama ini lo bangun bersama Teresa?”
Bahagia? Kenyataannya akupun bahagia saat bersama Nadya.
***
Malam ini untuk pertama kali kuajak Teresa kencan di restoran Portugis bernama Vasco Da Gama, menikmati beragam menu yang Teresa bilang menggugah selera. Namun aku tak mampu menikmatinya. Kuakui isi kepalaku menjalar ke mana-mana. Terutama soal keputusanku mengambil langkah yang selama ini terasa gamang. Ya, malam ini aku harus mengambil satu langkah pasti.
“Sayang, kok ngelamun terus. Ada apa sih?”
Jemari Teresa terasa hangat di atas punggung jemariku. Aku memberinya seulas senyum. “Sayang, minggu depan kita pulang, bagaimana?”
Perempuan itu sedikit mendongak. “Pulang? Memangnya urusanmu di sini sudah selesai?”
“Hampir selesai. Bosku memberi tugas baru di Jakarta. Kupikir ini bagus, kita bisa melanjutkan rencana pernikahan kita. Kamu tahu? Aku sudah bosan ditanya terus oleh Ayah dan Ibu.”
Teresa menaruh sendok ke mangkuk sup, lalu menundukkan wajahnya. “Kamu sendiri sudah mantap dengan rencana pernikahan kita?”
“Maksudmu? Aku tentu saja sudah siap. Kalau kamu sendiri?” aku berbalik tanya.
Teresa mengangkat wajahnya perlahan. “Sepertinya aku terlalu lama mengulur waktu. Baiklah, minggu depan kita pulang.”
“Teresa…” aku meremas jemari tangannya. “Kamu belum menjawab pertanyaanku. Kamu sudah siap dengan pernikahan kita?” tanyaku sekali lagi.
“Iya. Aku siap.”
Aku memperhatikan di kedalaman matanya. Kamu meragu, Sayang. Aku bisa melihatnya.
“Berhenti ah liatin aku kayak gitu,” gerutunya. “Kamu takut ya aku batalin pernikahan kita?”
“Iya,” jawabku jujur. “Apalagi semenjak kehadiran si Anthony itu. Aku takut pikiranmu teracuni olehnya.”
“Hei… kok gitu ngomongnya? Anthony itu orang baik. Inget, dia yang nolong aku selama di sini!”
“Iya. Karena dia menyukaimu.”
“Shandi! Kamu gak pantes ngomong kayak gitu!” sergah Teresa. “Kamu kenapa sih? Apa gara-gara omongan dia kemarin?”
“Hm… maksudmu soal dia menyinggung Nadya?”
“Iya. Menurutku wajar Anthony bertanya-tanya seperti itu. Ada perempuan main di hotel lelaki, siapapun patut merasa curiga. Dan yang aku tahu, kamu gak pernah bisa berteman akrab dengan perempuan. Jujur saja, gak cuma Anthony, akupun punya tanda tanya besar.”
“Teresa… kok kamu malah ikut-ikutan menyerangku?”
“Kamu yang menyerangku duluan!” timpal Teresa seraya melempar tisu ke arah makanan. Tak lama ia bergegas meninggalkan meja kami.
“Teresa!” aku mengejarnya. “Tunggu Teresa!” perempuan itu malah mempercepat langkahnya. Sial! Aku telah mengacaukan kencan kami.
Dengan susah payah akhirnya aku berhasil meraih pergelangan tangannya di pelataran parkir.
“Maafkan aku!” aku mendekapnya erat. Sementara kekasihku tak memberi reaksi apapun. Ia hanya diam terpaku membiarkanku mengiba meminta maaf.
“Hatimu terselubung keraguan. Padahal kamu gak pernah tahu ada namamu di setiap bentangan jarak yang kujalani. Aku rindu kamu. Bahkan hingga detik inipun masih merindukanmu. Kamu tahu kenapa? karena kudapati sesuatu yang hilang dari binar matamu.”
“Maafkan aku… maaf,” lirihku.
“Yang sepantasnya merasa takut itu adalah aku. Aku takut telah terjadi sesuatu yang membuatmu perlahan meninggalkanku.”
“Tidak, Sayang. Aku akan ada buat kamu.”
Kali ini Teresa membalas dekapanku. Ia menangis terisak di atas bahuku mencoba menghilangkan semua bimbang yang merasuki hati kami berdua.
***
Dan inilah hal yang paling sulit kulakukan, saat menyambangi kediaman Nadya di kawasan Kampung Alor. Perempuan itu tidak terkejut saat mendapatiku berada di depan pintu rumahnya. Ia tahu aku akan datang dari pesan pendek yang kukirim kemarin malam.
“Masuk, Bang. Aku sengaja masak buat Abang hari ini.”
“Hei, tak perlu serepot itu menyambut Abang, kayak ke siapa aja.”
Perempuan itu tersenyum. “Gak apa-apa, Bang. Dulu kan aku pernah janji bakal masak sesuatu buat Abang.”
Aku tak mampu berkata-kata lagi. Hatiku sangat sakit harus memberinya luka untuk yang kedua kali. Sementara Nadya hanya menyunggingkan bibirnya seraya menarik pergelangan tanganku menuju meja makan. Benar juga, terhidang di sana menu makanan khas Indonesia yang lama sekali aku rindukan.
“Sop Buntut?”
“Jangan bilang kalo Abang gak suka makanan ini,” canda Nadya.
“Kejutan sekali. Dari mana kamu tahu makanan kesukaan Abang?”
“Tiga bulan cukup membuat aku mengenal seorang Maha Shandi Istanzia,” jawabnya tulus.
“Termasuk perasaan Abang, Nad?”
Perempuan itu mengangguk. “Termasuk perasaan Abang,” ia mengulang kembali ucapanku.
“Abang…”
“Huss…” Nadya menutup bibirku dengan telunjuknya. “Kita bicara lagi selepas makan, ya?”
Waktu merambat perlahan. Aku mencoba menikmati ketegangan ini dengan semangkup sup yang cukup membuai lidah. Hingga setengah jam berlalu kami masih berada dalam keheningan kata.
“Gimana, Bang? Enak?”
Aku mengangguk tanpa bersuara. Sementara Nadya mulai bangkit membereskan sisa makanan dan piring kotor.
“Kamu melayani Abang sangat baik hari ini.”
Lagi-lagi Nadya tersenyum. “Kalo tidak sekarang, kapan lagi?” dia mengedipkan matanya.
Tuhan, bagaimana aku harus memulainya? Aku tak ingin mengakhiri yang baru saja kumulai. Meski kusadari masa depanku akan menjadi taruhannya. Namun percakapan semalam bersama Teresa seolah membuatku harus melakukan ini. Benarkah aku masih mencintai Teresa? Sungguhkah aku harus melakukan ini?
Perlahan aku melangkah mengikuti jejak Nadya di dapur. Nampak dia tengah membersihkan piring bekas makan kami. Rasanya ingin melangkah lebih dekat dan merangkulnya. Namun entah kenapa, kaki ini terasa berat untuk kugerakkan.
“Minggu depan Abang akan pulang bersama Teresa,” terucap juga kalimat yang sejak tadi ingin kusampaikan. Sementara Nadya masih memunggungiku berlagak sibuk memainkan air, padahal aku tahu tak ada sisa piring kotor di sana. “Maafkan Abang, Nad. Abang gak tahu akhirnya akan seperti ini.”
Kali ini Nadya membalikkan badannya. Perlahan ia menghampiriku. Terasa sensasi dingin saat jemari itu menyentuh pipi. “Sudah kubilang sejak awal, aku tidak apa-apa. Abang gak perlu khawatirkan aku,” meski berusaha tegar, namun suaranya terdengar parau di telinga. Sangat menyakitiku. “Namun yang pasti aku menikmati kebersamaan kita.”
“Hati Abang sulit melepaskanmu,” lirihku.
“Seandainya aku meminta Abang untuk tinggal. Aku tahu Abang akan membalas dengan anggukan setuju. Maka semakin lengkaplah dosaku menghancurkan mimpi seseorang. Abang tenang saja. Meninggalkanku takkan membuat sosok Abang menjadi hina di mataku. Karena aku tahu cinta memiliki jalannya sendiri. Yang perlu dilakukan hanyalah mengikuti ke mana cinta membawa Abang pergi.”
Aku membalas senyumannya seraya menghapus air mata yang terlanjur berjatuhan. “Abang akan selalu mengingatmu. Semua kebaikanmu takkan hilang begitu saja,” tak banyak kata yang terucap meski sebenarnya ada banyak hal yang ingin kuungkapkan. “Abang pergi sekarang…” akhirnya kalimat perpisahan itu terucap juga. Tubuh ini perlahan bergerak. meninggalkan hatinya yang terluka karenaku.
“Aku cinta Abang.”
“Ya, Nadya. Abang pun mencintai kamu. Tapi akan menyakitkan bila kita teruskan cinta ini. Kamu tak pantas mencintai lelaki brengsek seperti Abang, yang mudah terombang-ambing karena cinta,” aku tak sanggup berbalik lalu menatap kepedihannya. Lebih baik aku pergi berlalu sebagai lelaki pengecut. Meninggalkan Nadya dengan perasaan hancurnya.
“Bang Shandi…” lirih namun pedih. Dia tak bisa mengejarku seolah tahu kami tak ditakdirkan untuk bersama. Hanya rintihannya yang terus membayangi ke mana pun aku pergi. Aku mencintaimu, Nad. Sungguh mencintaimu…
Aku pergi dengan dua rasa yang berseberangan. Kebahagiaan tak terkira saat merengkuh kekasih yang kurindu, berdampingan dengan sesalku menempatkan dia ke dalam palung kekecewaan.
Katakanlah itu cinta, meski hening dalam kata namun hangat dalam rasa. Bagaimanapun kutahu semua telah terlambat tuk kita sadari. Dan kau dengan tegar merelakanku untuk kembali ke jalan semula. Dalam hati tak hentinya kumerapal doa. Semoga kelak kutemukan jejakmu kembali di tapal batas kota ini.
Other Stories
Kukejar Impian Besarku
Ramon, Yongki,Dino,Jodi,Eka adalah sekumpulan anak band yg rutin manggung di sebuah cafe d ...
Hati Yang Beku
Jasmine menatap hamparan metropolitan dari lantai tiga kostannya. Kerlap-kerlip ibukota ...
Nestapa
Masa kecil Zaskia kurang bahagia, karena kedua orangtua memilih bercerai. Ayahnya langsung ...
DI BAWAH PANJI DIPONEGORO
Damar, seorang petani terpanggil jiwanya untuk berjuang mengusir penjajah Belanda di bawah ...
Cangkul Yang Dalam ( Halusinada )
Alya sendirian di dapur. Dia terlihat masih kesal. Matanya tertuju ke satu set pisau yang ...
Waktu Tambahan
Seorang mantan pesepakbola tua yang karirnya sudah redup, berkesempatan untuk melatih seke ...