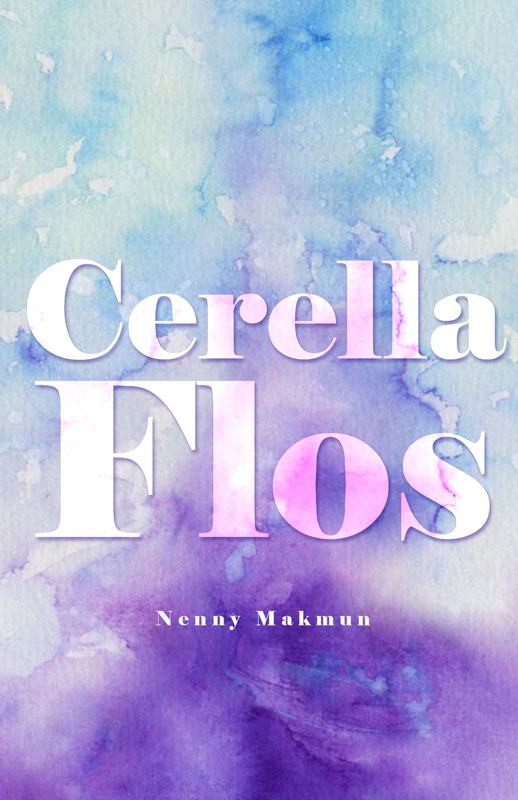Cemoohan Di Lapangan
Pagi itu, udara terasa begitu segar. Aku melangkah ke sekolah dengan langkah yang lebih ringan dari biasanya. Di dalam tas lusuhku, bukan hanya buku pelajaran, tapi juga buku jalan menuju puncak dan buku arsitektur dari Ibu Lia.
Keduanya bagaikan tameng yang melindungiku dari bisikan negatif dan tatapan meremehkan. Aku merasa tak terhentikan.
Namun, semangatku diuji saat jam istirahat tiba. Aku sedang duduk sendirian di pinggir lapangan, menggambar sketsa bangunan di buku catatanku.
Aku membayangkan sebuah rumah yang dibangun dari bahan daur ulang, sebuah konsep yang terinspirasi dari pekerjaanku sebagai pemulung. Tiba-tiba, bayangan Riko dan gengnya menutupi sinar matahari.
"Wah, wah, lihat ini," kata Riko sambil mengambil buku gambarku. Matanya membulat saat melihat sketsa-sketsa yang kutorehkan. "Rumah dari botol plastik? Gedung dari kaleng bekas? Mau jadi arsitek rongsokan, Ryan?"
Tawa teman-temannya pecah. Ejekan itu bagaikan belati yang menusuk. Panas hatiku, tapi aku berusaha untuk tetap tenang.
Aku tidak ingin membalas mereka dengan kata-kata. Aku ingin membalas mereka dengan pencapaian.
"Kembalikan bukuku, Riko," kataku, berusaha menjaga suaraku agar tidak bergetar.
"Kenapa? Kamu malu? Memang seharusnya kamu malu. Cita-citamu itu cuma mimpi kosong, Ryan. Kamu pikir kamu bisa jadi arsitek cuma dari buku bekas?" Riko melempar bukuku ke tanah, dan halamannya terbuka di bagian sketsa yang paling kusukai.
Aku menunduk, mengambil buku itu dengan hati-hati. Debu menempel di sketsaku, merusak garis-garis yang kubuat dengan susah payah.
Mataku berkaca-kaca. Bukan karena aku merasa lemah, tapi karena aku marah. Marah pada ketidakadilan. Marah pada mereka yang hanya bisa meremehkan tanpa pernah tahu seberapa besar perjuangan di balik setiap sketsa itu.
Aku bangkit, menatap lurus ke mata Riko. Untuk pertama kalinya, aku tidak menunduk. "Kamu boleh meremehkan cita-citaku," kataku dengan suara yang tegas, "Tapi kamu tidak bisa meremehkan kerja kerasku. Kamu punya semua, tapi kamu tidak punya semangat. Aku mungkin tidak punya apa-apa, tapi aku punya mimpi yang tidak bisa kamu beli."
Wajah Riko berubah. Matanya yang tadinya penuh ejekan, kini menunjukkan sedikit rasa terkejut. Teman-temannya terdiam. Mereka tidak menyangka aku akan membalas dengan kata-kata setajam itu.
Aku segera membalikkan badan dan berjalan pergi. Aku tidak tahu dari mana kekuatan itu datang, tapi aku merasa seperti telah memenangkan sebuah pertempuran.
Aku menyendiri di belakang sekolah, duduk di bawah pohon mangga. Aku membuka kembali buku jalan menuju puncak. Kisah-kisah di dalamnya terasa lebih relevan dari sebelumnya. Aku membaca kisah seorang penemu yang diejek oleh seluruh desa karena ide-ide gilanya. Ia tidak membalas, melainkan terus bekerja, siang dan malam, hingga akhirnya ia berhasil membuktikan pada mereka bahwa mereka salah.
Aku sadar, Riko dan teman-temannya adalah bagian dari ujianku. Mereka adalah tantangan yang harus kuhadapi. Aku tidak boleh membiarkan kata-kata mereka meruntuhkan semangatku. Sebaliknya, aku harus menjadikannya bahan bakar. Bahan bakar untuk membuktikan bahwa aku bisa.
Malam harinya, aku menceritakan kejadian itu pada Ayah. Ayah mendengarkan dengan seksama, wajahnya yang lelah terlihat khawatir. "Mereka bodoh, Nak," katanya pelan, "Mereka hanya bisa melihat apa yang ada di permukaan. Mereka tidak bisa melihat apa yang ada di dalam hatimu."
"Tapi rasanya sakit, Yah," kataku, air mata yang kutahan sejak siang akhirnya tumpah.
Ayah memelukku erat-erat, "Terkadang, Nak, rasa sakit itu adalah pelajaran. Itu mengajarkanmu untuk menjadi lebih kuat. Jangan biarkan mereka mengendalikan emosimu. Fokus pada mimpimu. Jadikan cemoohan mereka sebagai motivasi, bukan sebagai hambatan."
Kata-kata Ayah bagaikan obat penawar yang menenangkan jiwaku. Aku tahu ia benar. Rasa sakit itu memang ada, tapi itu tidak boleh menghentikanku. Aku harus terus melangkah. Aku harus membuktikan pada Riko dan teman-temannya bahwa aku tidak akan menyerah.
Keesokan harinya, aku kembali ke sekolah. Aku berjalan tegak, menatap lurus ke depan. Aku tidak lagi peduli dengan bisikan mereka. Aku tahu siapa diriku. Aku tahu apa yang harus kuusahakan. Dan aku tahu, suatu hari nanti, Riko dan teman-temannya akan melihatku bukan sebagai anak pemulung, tapi sebagai Ryan si arsitek.
Dan di hari itu, aku tidak akan merasa marah lagi. Aku hanya akan merasa bangga. Bangga karena aku tidak pernah menyerah. Bangga karena aku tidak pernah membiarkan cemoohan mereka menghentikan langkahku.
Aku kini menyadari, perjuangan terbesarku bukanlah melawan kemiskinan, tapi melawan keraguan yang ditanamkan oleh orang lain. Dan aku tidak akan membiarkan mereka menang. Tidak akan pernah.
****
Setelah kejadian di lapangan, ada perubahan yang sangat jelas dalam diriku. Aku tidak lagi menganggap Riko sebagai musuh, melainkan sebagai sebuah tantangan. Setiap kali aku merasa lelah, setiap kali aku merasa ingin menyerah, bayangan wajah Riko yang meremehkan muncul. Dan itu cukup untuk membakar kembali semangatku.
Aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu di perpustakaan sekolah. Aku tidak hanya membaca buku-buku arsitektur, tetapi juga buku-buku tentang fisika, matematika, dan seni. Aku tahu, seorang arsitek harus menguasai banyak hal. Aku membuat catatan kecil di buku catatanku, mencoret-coret ide-ide, dan membuat sketsa.
Suatu hari, Ibu Lia menghampiriku di perpustakaan. Ia melihat sketsa-sketsaku, dan senyumnya mengembang. "Ryan, kamu benar-benar serius dengan mimpimu, ya?" tanyanya. Aku mengangguk. "Saya tidak punya pilihan, Bu. Ini satu-satunya jalan saya," jawabku jujur.
"Itu salah, Nak. Semua orang punya pilihan," katanya lembut, "Kamu punya pilihan untuk menyerah, atau pilihan untuk terus berjuang. Dan kamu memilih yang kedua."
Ibu Lia mengusap kepalaku, sebuah sentuhan yang terasa begitu tulus, "Ibu sangat bangga padamu."
Kata-kata Ibu Lia itu sangat berarti bagiku. Lebih dari sekadar nilai A di rapor, lebih dari pujian guru lainnya. Dukungan tulus dari orang-orang yang peduli membuatku merasa tak terkalahkan.
Hidupku terasa lebih sibuk dari sebelumnya.
Pagi aku sekolah, pulang sekolah membantu Ayah memulung, sore hingga malam aku belajar dan membuat sketsa. Terkadang, aku merasa sangat lelah. Mataku seringkali terasa berat, dan tubuhku terasa pegal. Namun, setiap kali aku menatap jendela usang di kamarku, aku selalu ingat pada janji yang telah kubuat.
Jendela itu tidak lagi buram.
Setiap hari, aku membersihkannya. Aku ingin memastikan aku melihat dunia dengan jelas tanpa keraguan. Dunia di luar sana masih sama. Mobil-mobil mewah masih melintas.
Anak-anak lain masih tertawa riang. Tapi, pandanganku telah berubah. Aku tidak lagi melihat mereka sebagai orang-orang yang beruntung. Aku melihat mereka sebagai orang-orang yang mungkin tidak tahu seberapa beruntungnya mereka.
Aku tidak lagi merasa iri. Aku kini memiliki jalanku sendiri. Jalan yang mungkin lebih sulit, panjang, dan berliku. Tapi aku tahu, di ujung jalan itu, ada sebuah puncak. Dan aku siap mendaki.
Keduanya bagaikan tameng yang melindungiku dari bisikan negatif dan tatapan meremehkan. Aku merasa tak terhentikan.
Namun, semangatku diuji saat jam istirahat tiba. Aku sedang duduk sendirian di pinggir lapangan, menggambar sketsa bangunan di buku catatanku.
Aku membayangkan sebuah rumah yang dibangun dari bahan daur ulang, sebuah konsep yang terinspirasi dari pekerjaanku sebagai pemulung. Tiba-tiba, bayangan Riko dan gengnya menutupi sinar matahari.
"Wah, wah, lihat ini," kata Riko sambil mengambil buku gambarku. Matanya membulat saat melihat sketsa-sketsa yang kutorehkan. "Rumah dari botol plastik? Gedung dari kaleng bekas? Mau jadi arsitek rongsokan, Ryan?"
Tawa teman-temannya pecah. Ejekan itu bagaikan belati yang menusuk. Panas hatiku, tapi aku berusaha untuk tetap tenang.
Aku tidak ingin membalas mereka dengan kata-kata. Aku ingin membalas mereka dengan pencapaian.
"Kembalikan bukuku, Riko," kataku, berusaha menjaga suaraku agar tidak bergetar.
"Kenapa? Kamu malu? Memang seharusnya kamu malu. Cita-citamu itu cuma mimpi kosong, Ryan. Kamu pikir kamu bisa jadi arsitek cuma dari buku bekas?" Riko melempar bukuku ke tanah, dan halamannya terbuka di bagian sketsa yang paling kusukai.
Aku menunduk, mengambil buku itu dengan hati-hati. Debu menempel di sketsaku, merusak garis-garis yang kubuat dengan susah payah.
Mataku berkaca-kaca. Bukan karena aku merasa lemah, tapi karena aku marah. Marah pada ketidakadilan. Marah pada mereka yang hanya bisa meremehkan tanpa pernah tahu seberapa besar perjuangan di balik setiap sketsa itu.
Aku bangkit, menatap lurus ke mata Riko. Untuk pertama kalinya, aku tidak menunduk. "Kamu boleh meremehkan cita-citaku," kataku dengan suara yang tegas, "Tapi kamu tidak bisa meremehkan kerja kerasku. Kamu punya semua, tapi kamu tidak punya semangat. Aku mungkin tidak punya apa-apa, tapi aku punya mimpi yang tidak bisa kamu beli."
Wajah Riko berubah. Matanya yang tadinya penuh ejekan, kini menunjukkan sedikit rasa terkejut. Teman-temannya terdiam. Mereka tidak menyangka aku akan membalas dengan kata-kata setajam itu.
Aku segera membalikkan badan dan berjalan pergi. Aku tidak tahu dari mana kekuatan itu datang, tapi aku merasa seperti telah memenangkan sebuah pertempuran.
Aku menyendiri di belakang sekolah, duduk di bawah pohon mangga. Aku membuka kembali buku jalan menuju puncak. Kisah-kisah di dalamnya terasa lebih relevan dari sebelumnya. Aku membaca kisah seorang penemu yang diejek oleh seluruh desa karena ide-ide gilanya. Ia tidak membalas, melainkan terus bekerja, siang dan malam, hingga akhirnya ia berhasil membuktikan pada mereka bahwa mereka salah.
Aku sadar, Riko dan teman-temannya adalah bagian dari ujianku. Mereka adalah tantangan yang harus kuhadapi. Aku tidak boleh membiarkan kata-kata mereka meruntuhkan semangatku. Sebaliknya, aku harus menjadikannya bahan bakar. Bahan bakar untuk membuktikan bahwa aku bisa.
Malam harinya, aku menceritakan kejadian itu pada Ayah. Ayah mendengarkan dengan seksama, wajahnya yang lelah terlihat khawatir. "Mereka bodoh, Nak," katanya pelan, "Mereka hanya bisa melihat apa yang ada di permukaan. Mereka tidak bisa melihat apa yang ada di dalam hatimu."
"Tapi rasanya sakit, Yah," kataku, air mata yang kutahan sejak siang akhirnya tumpah.
Ayah memelukku erat-erat, "Terkadang, Nak, rasa sakit itu adalah pelajaran. Itu mengajarkanmu untuk menjadi lebih kuat. Jangan biarkan mereka mengendalikan emosimu. Fokus pada mimpimu. Jadikan cemoohan mereka sebagai motivasi, bukan sebagai hambatan."
Kata-kata Ayah bagaikan obat penawar yang menenangkan jiwaku. Aku tahu ia benar. Rasa sakit itu memang ada, tapi itu tidak boleh menghentikanku. Aku harus terus melangkah. Aku harus membuktikan pada Riko dan teman-temannya bahwa aku tidak akan menyerah.
Keesokan harinya, aku kembali ke sekolah. Aku berjalan tegak, menatap lurus ke depan. Aku tidak lagi peduli dengan bisikan mereka. Aku tahu siapa diriku. Aku tahu apa yang harus kuusahakan. Dan aku tahu, suatu hari nanti, Riko dan teman-temannya akan melihatku bukan sebagai anak pemulung, tapi sebagai Ryan si arsitek.
Dan di hari itu, aku tidak akan merasa marah lagi. Aku hanya akan merasa bangga. Bangga karena aku tidak pernah menyerah. Bangga karena aku tidak pernah membiarkan cemoohan mereka menghentikan langkahku.
Aku kini menyadari, perjuangan terbesarku bukanlah melawan kemiskinan, tapi melawan keraguan yang ditanamkan oleh orang lain. Dan aku tidak akan membiarkan mereka menang. Tidak akan pernah.
****
Setelah kejadian di lapangan, ada perubahan yang sangat jelas dalam diriku. Aku tidak lagi menganggap Riko sebagai musuh, melainkan sebagai sebuah tantangan. Setiap kali aku merasa lelah, setiap kali aku merasa ingin menyerah, bayangan wajah Riko yang meremehkan muncul. Dan itu cukup untuk membakar kembali semangatku.
Aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu di perpustakaan sekolah. Aku tidak hanya membaca buku-buku arsitektur, tetapi juga buku-buku tentang fisika, matematika, dan seni. Aku tahu, seorang arsitek harus menguasai banyak hal. Aku membuat catatan kecil di buku catatanku, mencoret-coret ide-ide, dan membuat sketsa.
Suatu hari, Ibu Lia menghampiriku di perpustakaan. Ia melihat sketsa-sketsaku, dan senyumnya mengembang. "Ryan, kamu benar-benar serius dengan mimpimu, ya?" tanyanya. Aku mengangguk. "Saya tidak punya pilihan, Bu. Ini satu-satunya jalan saya," jawabku jujur.
"Itu salah, Nak. Semua orang punya pilihan," katanya lembut, "Kamu punya pilihan untuk menyerah, atau pilihan untuk terus berjuang. Dan kamu memilih yang kedua."
Ibu Lia mengusap kepalaku, sebuah sentuhan yang terasa begitu tulus, "Ibu sangat bangga padamu."
Kata-kata Ibu Lia itu sangat berarti bagiku. Lebih dari sekadar nilai A di rapor, lebih dari pujian guru lainnya. Dukungan tulus dari orang-orang yang peduli membuatku merasa tak terkalahkan.
Hidupku terasa lebih sibuk dari sebelumnya.
Pagi aku sekolah, pulang sekolah membantu Ayah memulung, sore hingga malam aku belajar dan membuat sketsa. Terkadang, aku merasa sangat lelah. Mataku seringkali terasa berat, dan tubuhku terasa pegal. Namun, setiap kali aku menatap jendela usang di kamarku, aku selalu ingat pada janji yang telah kubuat.
Jendela itu tidak lagi buram.
Setiap hari, aku membersihkannya. Aku ingin memastikan aku melihat dunia dengan jelas tanpa keraguan. Dunia di luar sana masih sama. Mobil-mobil mewah masih melintas.
Anak-anak lain masih tertawa riang. Tapi, pandanganku telah berubah. Aku tidak lagi melihat mereka sebagai orang-orang yang beruntung. Aku melihat mereka sebagai orang-orang yang mungkin tidak tahu seberapa beruntungnya mereka.
Aku tidak lagi merasa iri. Aku kini memiliki jalanku sendiri. Jalan yang mungkin lebih sulit, panjang, dan berliku. Tapi aku tahu, di ujung jalan itu, ada sebuah puncak. Dan aku siap mendaki.
Other Stories
Cerella Flost
Aku pernah menjadi gadis yang terburuk.Tentu bukan karena parasku yang menjaminku menjadi ...
Blind
Ketika dunia gelap, seorang hampir kehilangan harapan. Tapi di tengah kegelapan, cinta dar ...
Pantaskah Aku Mencintainya?
Ika, seorang janda dengan putri pengidap kanker otak, terpaksa jadi kupu-kupu malam demi b ...
Tugas Akhir Vs Tugas Akhirat
Skripsi itu ibarat mantan toxic: ditinggal sakit, dideketin bikin stres. Allan, mahasiswa ...
Luka
LUKA Tiga sahabat. Tiga jalan hidup. Tiga luka yang tak kasatmata. Moana, pejuang garis ...
Tersesat
Qiran yang suka hal baru nekat mengakses deep web dan menemukan sebuah lagu, lalu memamerk ...