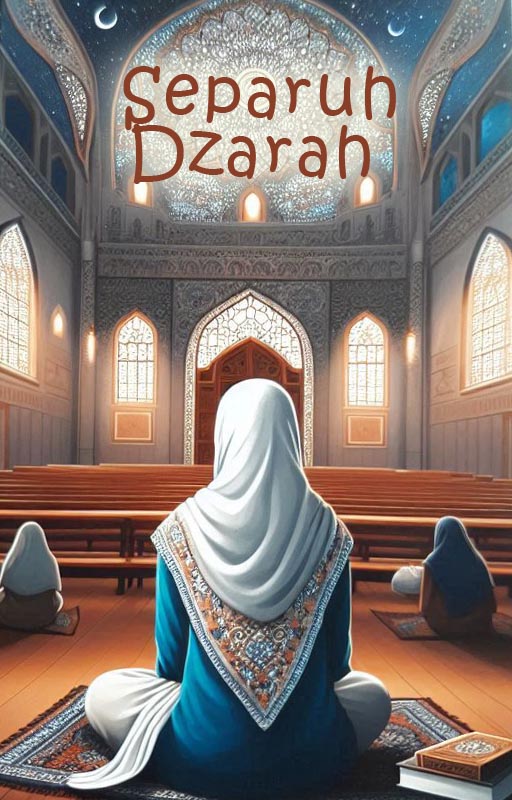BAB VIII: JANGKAR YANG TAK PERNAH TURUN
Panggilan yang Tidak Diduga
Hujan turun deras di Jogja. Arunika sedang membantu anak-anak menata buku yang basah karena atap bocor. Ia baru saja selesai menulis esai baru: “Mengajar di Bawah Atap Bocor: Ketika Semangat Lebih Keras dari Hujan.”
Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nomor asing.
“Halo, ini Kak Arunika?” tanya suara perempuan di seberang.
“Iya, saya sendiri. Ada yang bisa dibantu?”
“Saya dari panitia Festival Literasi Nasional. Kami membaca tulisanmu di Catatan dari Gang Kecil. Luar biasa. Kami ingin mengundangmu jadi pembicara utama di sesi ‘Suara dari Pinggiran’.”
Arunika terdiam.
Pembicara utama?
Di depan ratusan orang?
Di gedung besar?
“Saya… saya bukan siapa-siapa,” jawabnya pelan.
“Saya cuma relawan. Saya bahkan nggak kuliah.”
“Justru karena itu,” kata perempuan itu lembut.
“Kami butuh suara yang nyata. Yang pernah jatuh. Yang pernah ragu. Yang akhirnya bangkit bukan karena keberuntungan, tapi karena terus mencoba. Kamu adalah suara itu.”
Arunika menutup telepon. Duduk di lantai. Hujan masih mengguyur. Tapi hatinya lebih kacau dari langit.
Ia merasa seperti kapal kecil yang tiba-tiba diminta berlayar di tengah badai.
Rasa Ragu yang Kembali
Malam itu, Arunika tidak bisa tidur.
Ia membuka jurnalnya, tapi tidak bisa menulis.
Pikirannya dipenuhi suara-suara:
“Siapa kamu? Kamu bukan sarjana.”
“Orang-orang di sana pasti lebih pintar.”
“Kalau kamu gagal di panggung, semua orang akan tahu: kamu cuma penipu.”
Ia pergi ke atap. Duduk sendiri. Memandang langit yang gelap. Tidak ada bintang. Hanya awan kelam.
Ia berbisik:
“Laut… aku takut. Aku takut mengecewakan lagi.”
Ia tidak bisa memantau ombak, apakah menjawab atau tidak. Tapi angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah — seperti bau laut saat hujan turun di pantai.
Seperti mengingatkan:
"Kamu pernah bertahan saat semua ombak melawan. Kenapa takut pada satu panggung?"
Esok harinya, Dina datang dengan wajah berbinar.
“Kak! Aku dengar kamu mau bicara di acara besar! Aku baca di grup WhatsApp Ibu!”
Arunika tersenyum kaku. “Iya, Din. Tapi aku belum tahu mau ngomong apa.”
Dina menatapnya serius. “Katakan yang sebenarnya. Seperti yang kamu tulis di blog. Seperti yang kamu ajarkan ke kita.”
“Tapi aku takut salah, Din.” Lirih Arunika, suaranya sangat lemas— hampir tidak terdengar.
Dina menggeleng. “Kamu pernah bilang, Kak: ‘Yang penting bukan seberapa bagus kamu bicara, tapi seberapa tulus kamu berkata.’ Aku ingat itu.”
Arunika terdiam.
Anak kecil ini mengingatkannya pada nilai yang hampir ia lupakan.
Di jurnalnya, ia menulis:
“Aku lupa. Aku bukan di sini karena gelar. Aku di sini karena hati. Dan hatiku tahu: aku harus bicara. Bukan untuk dipuji. Tapi untuk mereka yang masih diam di kegelapan.”
Pertemuan dengan Kanaya
Dua minggu sebelum acara, Arunika datang ke lokasi acara untuk gladi bersih. Di sana, ia bertemu Kanaya, aktivis muda dari komunitas disabilitas, yang juga akan tampil.
Kanaya tuli sejak lahir, tapi ia berbicara dengan bahasa isyarat, dan menulis dengan kekuatan yang luar biasa. Ia membawa buku kecil berjudul: “Diam Bukan Kebisuan.”
Mereka berbincang lewat notes di ponsel.
Kanaya: “Aku baca tulisanmu. Kamu bicara tentang kegagalan seperti laut. Aku suka itu. Aku juga punya laut: sunyi. Tapi dari sunyi, aku belajar mendengar lebih dalam.”
Arunika: “Aku takut bicara di depan orang banyak. Aku takut tidak cukup baik.”
Kanaya: “Kamu tidak perlu sempurna. Kamu hanya perlu jujur. Dunia butuh suara yang retak, bukan yang mengkilap.”
Arunika menatap Kanaya.
Di matanya, ia melihat kekuatan yang tidak pernah ia miliki.
Orang ini tidak bisa mendengar, tapi ia lebih banyak “mendengar” daripada siapa pun.
Sepulang dari gladi bersih, Arunika mulai latihan berbicara. Ia merekam dirinya di ponsel. Tapi setiap kali menonton, ia merasa ingin menyerah.
Suara gemetar.
Jeda yang terlalu lama.
Kata-kata yang terasa datar.
Ia hampir menyerah. Sampai Langit berkata:
“Kamu tidak perlu jadi pembicara hebat. Kamu hanya perlu jadi Arunika yang sebenarnya.”
Malam itu, Arunika kembali ke pantai — dalam imajinasinya. Ia membayangkan dirinya duduk di batu karang, berbicara pada laut.
“Aku bukan apoteker. Aku bukan dokter. Aku bukan sarjana.
Tapi aku pernah menangis di kamar karena merasa gagal.
Aku pernah ingin menyerah.
Tapi aku terus berjalan.
Dan hari ini, aku di sini.
Bukan karena aku hebat.
Tapi karena aku tidak berhenti.”
Ketika ia mengucapkannya dengan suara pelan, matanya berkaca-kaca.
Tapi kali ini, bukan karena takut.
Tapi karena ia merasa benar.
Hari yang Menentukan
Hari H tiba.
Gedung pertemuan megah. Lampu sorot. Ratusan orang duduk diam. Di atas panggung, nama Arunika terpampang besar:
“Arunika – Dari Gagal ke Gema”
Ia berdiri di belakang panggung, jantung berdebar kencang. Ia memegang kalung kerang. Menatap langit dari jendela kecil.
Langit menggenggam tangannya. “Kamu siap?”
Arunika mengangguk. Tapi hatinya masih gemetar.
Lalu ia melihat Kanaya. Kanaya mengangkat satu jari, lalu menunjuk hatinya.
“Dari sini. Bicara dari sini.”
Arunika menarik napas.
Pembawa acara memanggil namanya.
“Sekarang, mari kita sambut Arunika — seorang relawan dari desa pesisir, penulis dari gang kecil, dan suara bagi yang tak terdengar.”
Arunika naik ke panggung. Lampu menyilaukan. Ia melihat lautan wajah. Tapi ia tidak melihat mereka. Ia melihat dirinya yang dulu — yang menangis di kamar, yang merasa tak punya masa depan.
Ia menggenggam mic yang telah diberikkan,
“Saya bukan siapa-siapa,” katanya pelan.
“Saya lulusan SMK Farmasi. Saya gagal masuk kuliah. Saya tidak punya uang. Saya pernah merasa dunia sudah berakhir.”
Ia berhenti. Napasnya berat. Tapi ia lanjutkan.
“Tapi saya belajar satu hal dari laut: surut bukan berarti kering.
Surut hanya persiapan untuk pasang.
Kegagalan bukan akhir.
Itu hanya tanda bahwa hidup sedang mengarahkanmu ke tempat yang lebih tepat.”
Suara di ruangan mulai tenang. Tidak ada bisik. Hanya napas yang tertahan.
“Saya datang ke Jogja bukan untuk menjadi pahlawan. Saya datang karena saya butuh tempat pulang.
Dan saya menemukannya di sini — di antara anak-anak yang tersenyum meski tidak punya sepatu.
Di antara tulisan yang membuat orang asing berkata: ‘Terima kasih, aku tidak sendiri.’”
Ia menatap penonton dengan tenang, satu persatu, menyusuri bak deruan ombak kecil yang menyapu seluruh pesisir laut. Ia tau, kali ini yang berbicara adalah lautan yang bersemayam dalam sukmanya.
“Jika kamu sedang jatuh, jangan menyerah.
Jika kamu merasa tidak cukup baik, teruslah berjalan.
Karena yang penting bukan seberapa cepat kamu sampai.
Tapi seberapa dalam kamu hidup.”
Ia menutup dengan kalimat terakhir:
“Jangkarmu tak pernah boleh kau turunkan.
Karena jangkarmu adalah harapan.
Dan harapan tidak pernah mati.”
Lama diam.
Lalu — tepuan tangan meledak.
Orang-orang berdiri. Beberapa menangis. Kanaya tersenyum, memberi jempol.
Arunika menunduk. Air mata mengalir.
Tapi kali ini lagi lagi bukan karena kesedihan.
Tapi karena ia tahu:
ia telah pulang.
Di belakang panggung, banyak orang ingin bertemu.
Seorang ibu berkata: “Anak saya putus sekolah. Setelah baca tulisanmu, dia mau coba lagi.”
Seorang mahasiswa: “Saya mau drop out. Tapi kamu mengingatkan saya: jangan menyerah.”
Seorang guru: “Saya akan bawa metodemu ke sekolah.”
Arunika memeluk mereka satu per satu.
Ia tidak merasa hebat.
Tapi ia merasa berguna.
Kanaya mendekat. Mereka berpelukan. Lalu Kanaya menulis di notes:
“Kamu bukan hanya bicara. Kamu menyembuhkan. Terima kasih.”
Arunika hanya bisa mengangguk dengan senyuman seteduh senja diufuk timur.
Laut yang Menyaksikan
Malam itu, Arunika tidak langsung pulang. Ia naik ke atap rumah komunitas. Menatap langit.
Ia membuka jurnal:
“Aku dulu takut gagal. Sekarang, aku takut tidak mencoba.
Aku dulu takut mengecewakan. Sekarang, aku takut diam.
Aku bukan pemenang. Aku bukan juara. Tapi aku adalah orang yang terus berjalan.
Dan itu sudah cukup.
Terima kasih, Laut. Karena kamu mengajariku bahwa jangkar tidak perlu diturunkan. Cukup dipegang erat, meski ombak bergulung.”
Ia menutup jurnal. Angin berhembus pelan, Membelai surai hitamnya yang terurai.
Kembali ke Asal
Beberapa minggu kemudian, Arunika menerima surat dari ayahnya.
“Nak, kami lihat videomu di internet. Semua orang di desa nonton. Nenek Laut bilang, ‘Aku tahu dia akan jadi ombak besar.’
Ayah bangga. Bukan karena kamu di panggung. Tapi karena kamu tetap jadi anak laut yang rendah hati.
Pulanglah. Lautmu rindu.”
Arunika tersenyum. Ia tahu:
Saatnya pulang.
Hujan turun deras di Jogja. Arunika sedang membantu anak-anak menata buku yang basah karena atap bocor. Ia baru saja selesai menulis esai baru: “Mengajar di Bawah Atap Bocor: Ketika Semangat Lebih Keras dari Hujan.”
Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nomor asing.
“Halo, ini Kak Arunika?” tanya suara perempuan di seberang.
“Iya, saya sendiri. Ada yang bisa dibantu?”
“Saya dari panitia Festival Literasi Nasional. Kami membaca tulisanmu di Catatan dari Gang Kecil. Luar biasa. Kami ingin mengundangmu jadi pembicara utama di sesi ‘Suara dari Pinggiran’.”
Arunika terdiam.
Pembicara utama?
Di depan ratusan orang?
Di gedung besar?
“Saya… saya bukan siapa-siapa,” jawabnya pelan.
“Saya cuma relawan. Saya bahkan nggak kuliah.”
“Justru karena itu,” kata perempuan itu lembut.
“Kami butuh suara yang nyata. Yang pernah jatuh. Yang pernah ragu. Yang akhirnya bangkit bukan karena keberuntungan, tapi karena terus mencoba. Kamu adalah suara itu.”
Arunika menutup telepon. Duduk di lantai. Hujan masih mengguyur. Tapi hatinya lebih kacau dari langit.
Ia merasa seperti kapal kecil yang tiba-tiba diminta berlayar di tengah badai.
Rasa Ragu yang Kembali
Malam itu, Arunika tidak bisa tidur.
Ia membuka jurnalnya, tapi tidak bisa menulis.
Pikirannya dipenuhi suara-suara:
“Siapa kamu? Kamu bukan sarjana.”
“Orang-orang di sana pasti lebih pintar.”
“Kalau kamu gagal di panggung, semua orang akan tahu: kamu cuma penipu.”
Ia pergi ke atap. Duduk sendiri. Memandang langit yang gelap. Tidak ada bintang. Hanya awan kelam.
Ia berbisik:
“Laut… aku takut. Aku takut mengecewakan lagi.”
Ia tidak bisa memantau ombak, apakah menjawab atau tidak. Tapi angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah — seperti bau laut saat hujan turun di pantai.
Seperti mengingatkan:
"Kamu pernah bertahan saat semua ombak melawan. Kenapa takut pada satu panggung?"
Esok harinya, Dina datang dengan wajah berbinar.
“Kak! Aku dengar kamu mau bicara di acara besar! Aku baca di grup WhatsApp Ibu!”
Arunika tersenyum kaku. “Iya, Din. Tapi aku belum tahu mau ngomong apa.”
Dina menatapnya serius. “Katakan yang sebenarnya. Seperti yang kamu tulis di blog. Seperti yang kamu ajarkan ke kita.”
“Tapi aku takut salah, Din.” Lirih Arunika, suaranya sangat lemas— hampir tidak terdengar.
Dina menggeleng. “Kamu pernah bilang, Kak: ‘Yang penting bukan seberapa bagus kamu bicara, tapi seberapa tulus kamu berkata.’ Aku ingat itu.”
Arunika terdiam.
Anak kecil ini mengingatkannya pada nilai yang hampir ia lupakan.
Di jurnalnya, ia menulis:
“Aku lupa. Aku bukan di sini karena gelar. Aku di sini karena hati. Dan hatiku tahu: aku harus bicara. Bukan untuk dipuji. Tapi untuk mereka yang masih diam di kegelapan.”
Pertemuan dengan Kanaya
Dua minggu sebelum acara, Arunika datang ke lokasi acara untuk gladi bersih. Di sana, ia bertemu Kanaya, aktivis muda dari komunitas disabilitas, yang juga akan tampil.
Kanaya tuli sejak lahir, tapi ia berbicara dengan bahasa isyarat, dan menulis dengan kekuatan yang luar biasa. Ia membawa buku kecil berjudul: “Diam Bukan Kebisuan.”
Mereka berbincang lewat notes di ponsel.
Kanaya: “Aku baca tulisanmu. Kamu bicara tentang kegagalan seperti laut. Aku suka itu. Aku juga punya laut: sunyi. Tapi dari sunyi, aku belajar mendengar lebih dalam.”
Arunika: “Aku takut bicara di depan orang banyak. Aku takut tidak cukup baik.”
Kanaya: “Kamu tidak perlu sempurna. Kamu hanya perlu jujur. Dunia butuh suara yang retak, bukan yang mengkilap.”
Arunika menatap Kanaya.
Di matanya, ia melihat kekuatan yang tidak pernah ia miliki.
Orang ini tidak bisa mendengar, tapi ia lebih banyak “mendengar” daripada siapa pun.
Sepulang dari gladi bersih, Arunika mulai latihan berbicara. Ia merekam dirinya di ponsel. Tapi setiap kali menonton, ia merasa ingin menyerah.
Suara gemetar.
Jeda yang terlalu lama.
Kata-kata yang terasa datar.
Ia hampir menyerah. Sampai Langit berkata:
“Kamu tidak perlu jadi pembicara hebat. Kamu hanya perlu jadi Arunika yang sebenarnya.”
Malam itu, Arunika kembali ke pantai — dalam imajinasinya. Ia membayangkan dirinya duduk di batu karang, berbicara pada laut.
“Aku bukan apoteker. Aku bukan dokter. Aku bukan sarjana.
Tapi aku pernah menangis di kamar karena merasa gagal.
Aku pernah ingin menyerah.
Tapi aku terus berjalan.
Dan hari ini, aku di sini.
Bukan karena aku hebat.
Tapi karena aku tidak berhenti.”
Ketika ia mengucapkannya dengan suara pelan, matanya berkaca-kaca.
Tapi kali ini, bukan karena takut.
Tapi karena ia merasa benar.
Hari yang Menentukan
Hari H tiba.
Gedung pertemuan megah. Lampu sorot. Ratusan orang duduk diam. Di atas panggung, nama Arunika terpampang besar:
“Arunika – Dari Gagal ke Gema”
Ia berdiri di belakang panggung, jantung berdebar kencang. Ia memegang kalung kerang. Menatap langit dari jendela kecil.
Langit menggenggam tangannya. “Kamu siap?”
Arunika mengangguk. Tapi hatinya masih gemetar.
Lalu ia melihat Kanaya. Kanaya mengangkat satu jari, lalu menunjuk hatinya.
“Dari sini. Bicara dari sini.”
Arunika menarik napas.
Pembawa acara memanggil namanya.
“Sekarang, mari kita sambut Arunika — seorang relawan dari desa pesisir, penulis dari gang kecil, dan suara bagi yang tak terdengar.”
Arunika naik ke panggung. Lampu menyilaukan. Ia melihat lautan wajah. Tapi ia tidak melihat mereka. Ia melihat dirinya yang dulu — yang menangis di kamar, yang merasa tak punya masa depan.
Ia menggenggam mic yang telah diberikkan,
“Saya bukan siapa-siapa,” katanya pelan.
“Saya lulusan SMK Farmasi. Saya gagal masuk kuliah. Saya tidak punya uang. Saya pernah merasa dunia sudah berakhir.”
Ia berhenti. Napasnya berat. Tapi ia lanjutkan.
“Tapi saya belajar satu hal dari laut: surut bukan berarti kering.
Surut hanya persiapan untuk pasang.
Kegagalan bukan akhir.
Itu hanya tanda bahwa hidup sedang mengarahkanmu ke tempat yang lebih tepat.”
Suara di ruangan mulai tenang. Tidak ada bisik. Hanya napas yang tertahan.
“Saya datang ke Jogja bukan untuk menjadi pahlawan. Saya datang karena saya butuh tempat pulang.
Dan saya menemukannya di sini — di antara anak-anak yang tersenyum meski tidak punya sepatu.
Di antara tulisan yang membuat orang asing berkata: ‘Terima kasih, aku tidak sendiri.’”
Ia menatap penonton dengan tenang, satu persatu, menyusuri bak deruan ombak kecil yang menyapu seluruh pesisir laut. Ia tau, kali ini yang berbicara adalah lautan yang bersemayam dalam sukmanya.
“Jika kamu sedang jatuh, jangan menyerah.
Jika kamu merasa tidak cukup baik, teruslah berjalan.
Karena yang penting bukan seberapa cepat kamu sampai.
Tapi seberapa dalam kamu hidup.”
Ia menutup dengan kalimat terakhir:
“Jangkarmu tak pernah boleh kau turunkan.
Karena jangkarmu adalah harapan.
Dan harapan tidak pernah mati.”
Lama diam.
Lalu — tepuan tangan meledak.
Orang-orang berdiri. Beberapa menangis. Kanaya tersenyum, memberi jempol.
Arunika menunduk. Air mata mengalir.
Tapi kali ini lagi lagi bukan karena kesedihan.
Tapi karena ia tahu:
ia telah pulang.
Di belakang panggung, banyak orang ingin bertemu.
Seorang ibu berkata: “Anak saya putus sekolah. Setelah baca tulisanmu, dia mau coba lagi.”
Seorang mahasiswa: “Saya mau drop out. Tapi kamu mengingatkan saya: jangan menyerah.”
Seorang guru: “Saya akan bawa metodemu ke sekolah.”
Arunika memeluk mereka satu per satu.
Ia tidak merasa hebat.
Tapi ia merasa berguna.
Kanaya mendekat. Mereka berpelukan. Lalu Kanaya menulis di notes:
“Kamu bukan hanya bicara. Kamu menyembuhkan. Terima kasih.”
Arunika hanya bisa mengangguk dengan senyuman seteduh senja diufuk timur.
Laut yang Menyaksikan
Malam itu, Arunika tidak langsung pulang. Ia naik ke atap rumah komunitas. Menatap langit.
Ia membuka jurnal:
“Aku dulu takut gagal. Sekarang, aku takut tidak mencoba.
Aku dulu takut mengecewakan. Sekarang, aku takut diam.
Aku bukan pemenang. Aku bukan juara. Tapi aku adalah orang yang terus berjalan.
Dan itu sudah cukup.
Terima kasih, Laut. Karena kamu mengajariku bahwa jangkar tidak perlu diturunkan. Cukup dipegang erat, meski ombak bergulung.”
Ia menutup jurnal. Angin berhembus pelan, Membelai surai hitamnya yang terurai.
Kembali ke Asal
Beberapa minggu kemudian, Arunika menerima surat dari ayahnya.
“Nak, kami lihat videomu di internet. Semua orang di desa nonton. Nenek Laut bilang, ‘Aku tahu dia akan jadi ombak besar.’
Ayah bangga. Bukan karena kamu di panggung. Tapi karena kamu tetap jadi anak laut yang rendah hati.
Pulanglah. Lautmu rindu.”
Arunika tersenyum. Ia tahu:
Saatnya pulang.
Other Stories
Separuh Dzarah
Saat salam terakhir dalam salat mulai terdengar, di sana juga akan mulai terdengar suara ...
Bangkit Dari Luka
Almira Brata Qeenza punya segalanya. Kecuali satu hal, yaitu kasih sayang. Sejak kecil, ia ...
Cinta Buta
Marthy jatuh cinta pada Edo yang dikenalnya lewat media sosial dan rela berkorban meski be ...
DIARY SUPERHERO
lanjutan cerita kisah cinta superhero. dari sudut pandang Sefia. superhero berkekuatan tel ...
Dear Zalina
Zalina,murid baru yang menggemparkan satu sekolah karena pesona nya,tidak sedikit cowok ya ...
Erase
Devi, seorang majikan santun yang selalu menghargai orang lain, menenangkan diri di ruang ...